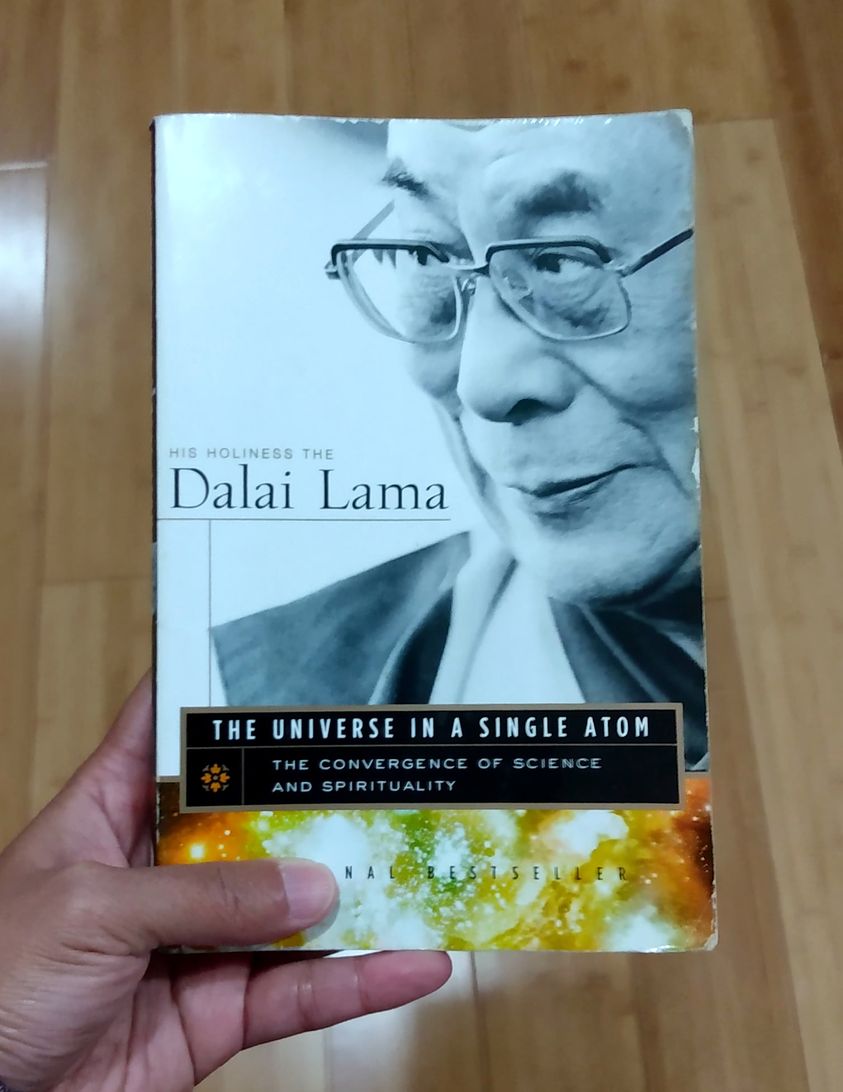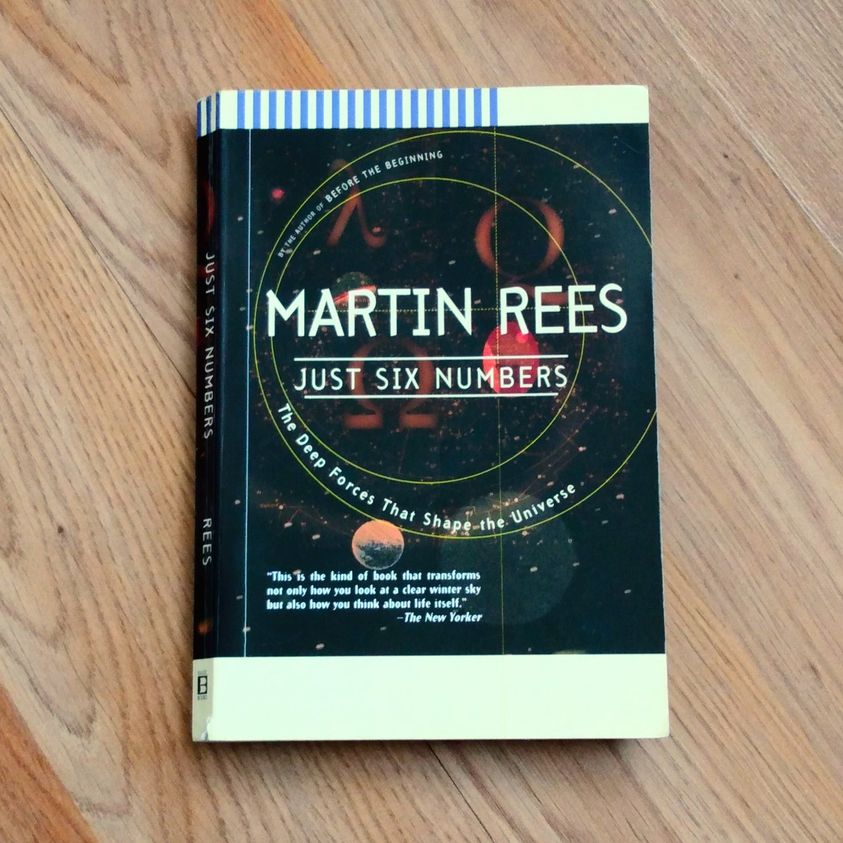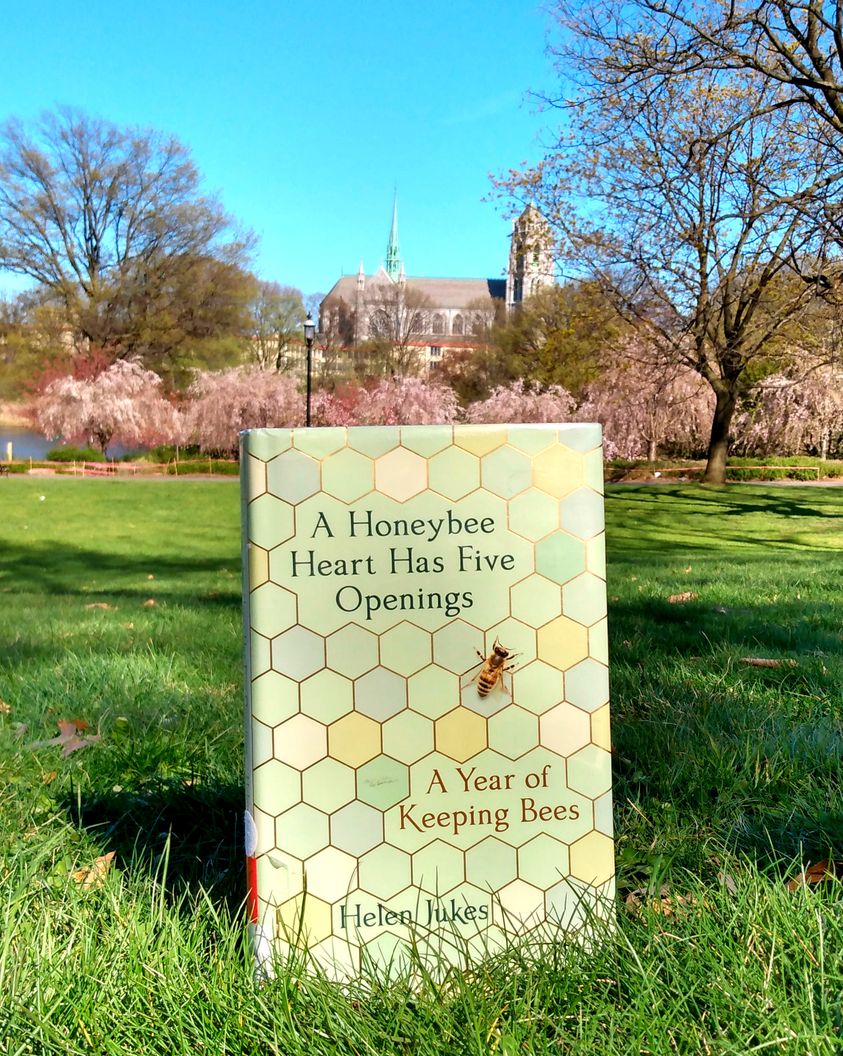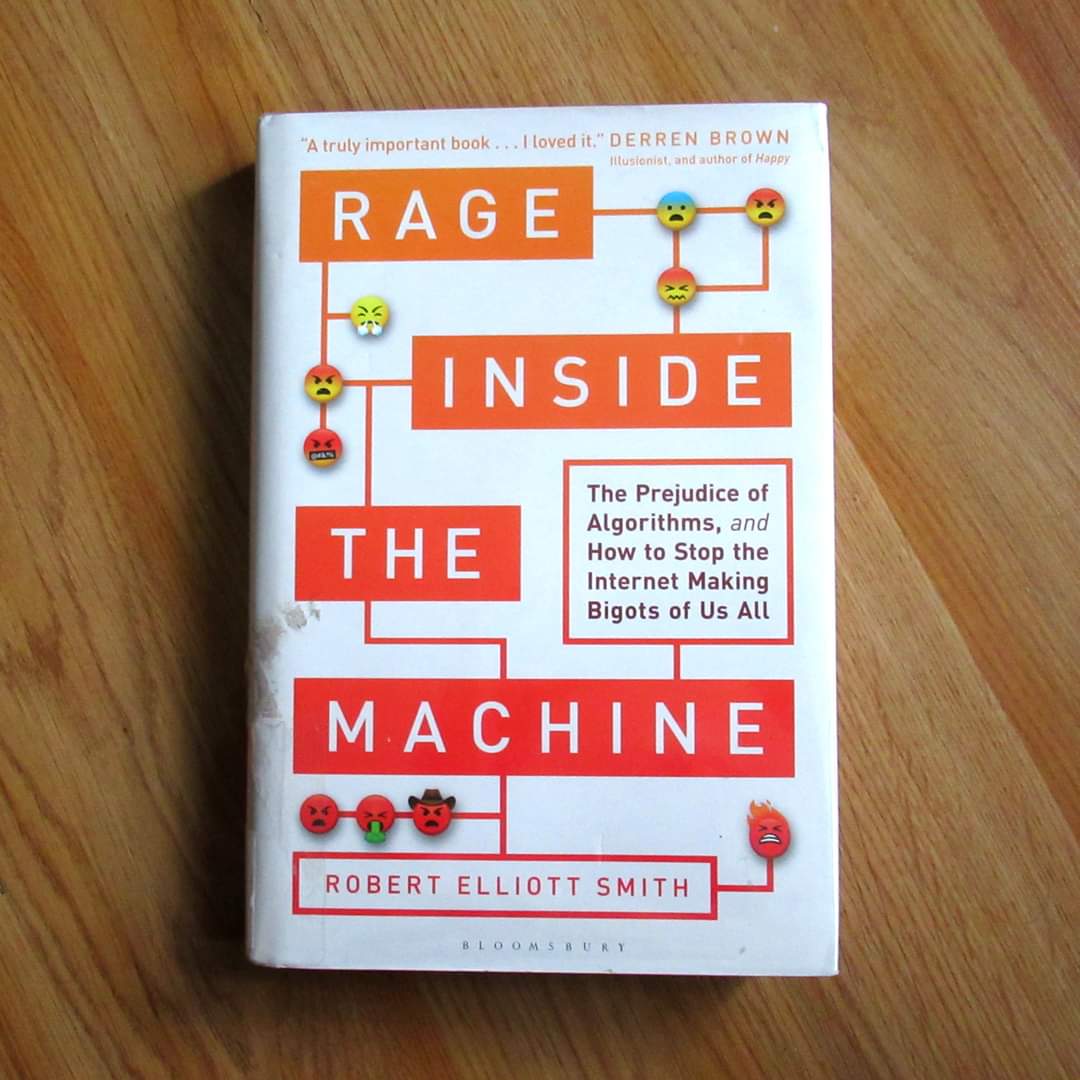HALUSINASI & STIGMA
Ada banyak istilah yang saya temukan memiliki arti berbeda di kalangan akademik dan di masyarakat yang mengakibatkan kesalahpahaman. Salah satunya yang sering saya temukan misalnya adalah “positive feedback loop”, yang di dunia akademik berarti ‘feedback loop yang menambah-nambah efeknya’, namun di masyarakat seringkali tertangkap sebagai ‘feedback yang bagus’ gara-gara ada kata ‘positive’.
Halusinasi, adalah salah satu istilah seperti ini. Kita yang awam terbiasa menyamakan halusinasi dengan delusi, bahkan mengasosiasikan mereka yang mengalaminya sebagai ‘terganggu otaknya’ dan bahkan ‘gila’. Karena stigma negatif inilah, orang-orang yang mengalami halusinasi seringkali tidak mau bercerita tentang apa yang dialaminya, bahkan tidak jarang menjadi depresi karena berpikir dirinya menuju kegilaan.
Padahal, istilah halusinasi di dunia akademik artinya ‘sekadar’ persepsi dalam bentuk pengalaman internal yang dialami seseorang dan tidak bisa ditangkap (dilihat, didengar, dirasakan) orang lain.
FYI, bahkan neuroscientist Anil Seth di buku “Being You” mengatakan bahwa hal yang kita sebut ‘realitas’ atau dunia nyata ini pun, bisa disebut sebuah halusinasi lho, sebab berupa persepsi yang dibentuk di dalam, dimodelkan oleh otak atas input dari tubuh, dan bisa jadi berbeda dengan apa yang muncul di kepala orang lain.
Karena itu, Oliver Sacks menulis buku ini antara lain untuk mengajak pembaca awam lebih memahami halusinasi.
Hallucinations
Oliver Sacks
Vintage Books (2013)
326 hal
Ketika kata ‘halusinasi’ pertama kali digunakan pada awal abad 16, ia hanya berarti ‘pikiran yang melayang’. Setelah 1830an, psikiater Prancis Esquirol memaknainya seperti yang kita (kurang lebih) pahami sekarang, sebagai ‘penampakan’. Arti kata yang tepatnya seringkali berbeda-beda, terutama karena fenomena ini sering beririsan dengan fenomena lain seperti ilusi dan mispersepsi. Tapi secara umum halusinasi dipahami sebagai persepsi yang muncul tapi tidak ada di realitas eksternal — melihat atau mendengar hal-hal yang tidak ada dunia luar. Bagi orang lain, orang yang berhalusinasi ini mengarang-ngarang saja, berimajinasi. Namun bagi yang bersangkutan, halusinasi terasa sangat nyata, bisa ‘dilihat’ atau ‘didengar’ seperti melihat dan mendengar objek yang nyata.
Halusinasi harus dibedakan dengan imajinasi. Ketika seseorang berimajinasi, membayangkan suatu gambaran visual atau skenario, biasanya hal itu terlihat di pikiran saja, tidak terproyeksikan ke ruang eksternal seperti halusinasi. Selain itu, dalam berimajinasi, seseorang berpartisipasi aktif secara sadar menciptakannya dan juga bisa mengubah-ubahnya semau-maunya. Ini sangat berbeda dengan halusinasi yang terjadi PADA seseorang tanpa bisa dikendalikan, dan yang bersangkutan hanya bisa mengamati/mengalami secara pasif saja. “(Hallucinations) appear and disappear whey THEY please, not when YOU please,” tulis Sacks.
Selain itu, ada juga yang disebut pseudo-halusinasi, yaitu halusinasi yang tidak terproyeksikan ke ruang eksternal, namun terlihat di ‘layar’ kelopak mata ketika mata terpejam. Ini biasanya terjadi sebelum atau sesudah tidur, dalam keadaan sadar atau setengah sadar. Namun karakteristiknya sama dengan halusinasi, yaitu tidak bisa dikontrol, hanya bisa diamati/alami.
Fenomena halusinasi sendiri mungkin sudah setua otak manusia, tapi pemahaman sains modern tentangnya semakin berkembang, terutama pasca adanya teknologi brain imaging. Berbagai budaya di dunia menganggap halusinasi, seperti juga mimpi, sebagai sesuatu yang istimewa, bahkan merupakan pengalaman yang banyak dicari melalui praktek-praktek spiritual, meditasi, mengasingkan diri, bahkan juga melalui obat-obatan atau ramuan psikedelik. Namun di budaya Barat, halusinasi lebih sering dianggap menandakan kegilaan atau kerusakan otak, meskipun mayoritas halusinasi tidak seperti itu. Stigma seperti ini tidak hanya datang dari masyarakat awam, malah seringkali pula datang dari kalangan medis.
Ada satu cerita di buku ini, tentang suatu eksperimen yang dilakukan oleh psikolog Stanford pada tahun 1973, di mana ia dan timnya berpura-pura menjadi pasien di beberapa rumah sakit berbeda. Semua mengaku “mendengar suara-suara” tanpa gejala lainnya, dan tanpa sejarah penyakit kejiwaan sebelumnya. Dan semua ‘pseudopasien’ ini divonis menderita schizophrenia, diberi resep obat anti-psikosis, dan dirawat sampai 2 bulan, hanya dari pengakuan itu saja! Ternyata di dunia psikiatri (pada saat itu) dan masyarakat secara umum, ‘mendengar suara-suara’ sudah identik dengan gangguan jiwa, dan tidak mungkin terjadi dalam kondisi ‘normal’. Kata pak Sacks, sebelumnya nggak begini. Dunia psikiatri sebelumnya lebih hati-hati mendiagnosis hal seperti ini, namun setelah adanya obat-obatan anti psikosis, dokter seolah ingin ‘cepat beres’ dengan meresepkan obat-obatan saja.
Ini stigma yang merusak, karenanya pasien seringkali tidak mau mengaku mengalami halusinasi karena khawatir dianggap gila. Karenanya pak Sack menulis buku ini, yang berupa semacam sejarah atau antologi kasus-kasus halusinasi, dengan menjabarkan pengalaman dan efek halusinasi pada orang yang mengalaminya, karena halusinasi hanya bisa dipahami dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Dengan membaca berbagai pengalaman halusinasi, semoga kita pembaca bisa lebih memahaminya sebagai bagian dari pengalaman manusia, tanpa langsung memberi stigma negatif.
Buku ini bercerita tentang berbagai macam halusinasi, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, dll, yang dialami pasien dr Sacks langsung atau kasus-kasus yang tercatat dalam artikel medis. Di dalamnya bahkan bercerita tentang pengalaman halusinasi pak Sacks sendiri, yg terjadi ketika ia mengalami migren, atau ketika ia bereksperimen dengan berbagai obat-obatan psikedelik semasa mahasiswa. Saya suka bagaimana pak Sacks membahas berbagai fenomena halusinasi ini, yang mungkin bagi banyak orang, atau yang mengaku-ngaku ‘manusia modern’ dianggap khayalan saja, namun ia mendekatinya secara simpatik dan dari posisi seseorang yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh. Selayaknya seorang ilmuwan yang rendah hati: penuh pertanyaan, dan tidak sok tahu.
Misalnya di bab pertama diceritakan kasus-kasus halusinasi visual yang rata-rata dialami mereka yang kehilangan penglihatan. Mereka ‘melihat’ halusinasi berbagai pemandangan, dengan gerakan mata seperti layaknya orang melihat, yang tidak terjadi jika hanya mengimajinasikan sesuatu. Halusinasi ini diceritakan seperti gambaran dinamis, seperti film, pemandangan yang tidak pernah dilihat/dialami sebelumnya. Contohnya seorang pasien menggambarkannya seperti sosok-sosok berpakaian budaya Timur yang cerah dan warna-warni, suasana bersalju, kuda, dll, padahal dia ada di dalam ruangan. Di dunia psikiatri Barat, gejala halusinasi visual seperti ini dinamakan Charles Bonnet Syndrome berdasarkan nama ilmuwan abad 18 yang pertama mencatat kasus-kasus seperti ini (kalau di kita mungkin disebut ‘penampakan’ aja ya).
Menurut Sacks, halusinasi visual yang paling umum berupa bentuk-bentuk geometri, dan yang paling sederhana berupa phosphene yaitu pendaran/kilatan cahaya dengan variasi terang/warna di penglihatan (kalau nggak kebayang, coba deh tutup mata dan tekan sedikit bola matanya, tidak lama akan ada sensasi-sensasi cahaya dan warna… itulah yang dinamakan phosphene).
Teknologi brain imaging telah sangat membantu ilmuwan sehingga mulai bisa mereka-reka bagian otak mana yang bertanggung jawab atas terjadinya jenis halusinasi yang berbeda-beda. Misalnya, halusinasi bentuk-bentuk wajah ternyata berkaitan dengan area otak yang berbeda dengan halusinasi teks. Bahkan halusinasi karakter kartun berkaitan dengan area yang lain lagi! Dan katanya, halusinasi musik adalah jenis halusinasi yang mengaktifkan paling banyak area otak.
Masih banyak lagi yang diceritakan di buku ini, seperti halusinasi yang muncul ketika demam, epilepsi, parkinson, dalam keadaan antara tidur dan bangun, sleep paralysis (ternyata memang istilah kita ‘ketindihan’ justru cocok dengan fenomena ini, karena konon awal mulanya kata ‘nightmare’ adalah folklore sosok wanita tua ‘old hag’ yang suka duduk di dada orang yang tidur sampai susah bernapas), dan lain-lain.
Dari berbagai kasus yang diceritakan di sini, juga observasi dan analisa dokter Sacks, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya sains sendiri belum bisa menjawab apa sebenarnya halusinasi itu. Ya, sains mulai bisa menjelaskan proses bagaimana halusinasi terjadi, ‘the HOW’, bahwa halusinasi terjadi ketika ada area-area otak tertentu yang somehow teraktifkan. Namun soal ‘the WHY’, mengapa halusinasi dengan berbagai keragaman pengalaman ini terjadi, bahkan juga pada mereka yang tidak mengalami kerusakan otak, orang yang ‘normal’, tidak mengalami epilepsi, tidak ini dan tidak itu.
Karenanya, paling tidak bagi saya pribadi, sikap yang paling tepat menghadapi halusinasi bukanlah langsung skeptis dengan tuduhan-tuduhan ‘kejam’ kegilaan dan sakit jiwa, namun lebih tepat jika kita menghadapinya dengan sikap keingintahuan ala ilmuwan yang rendah hati: penuh pertanyaan dan keinginan mengerti. Siapa tahu, ada hal baru yang dapat kita pelajari.