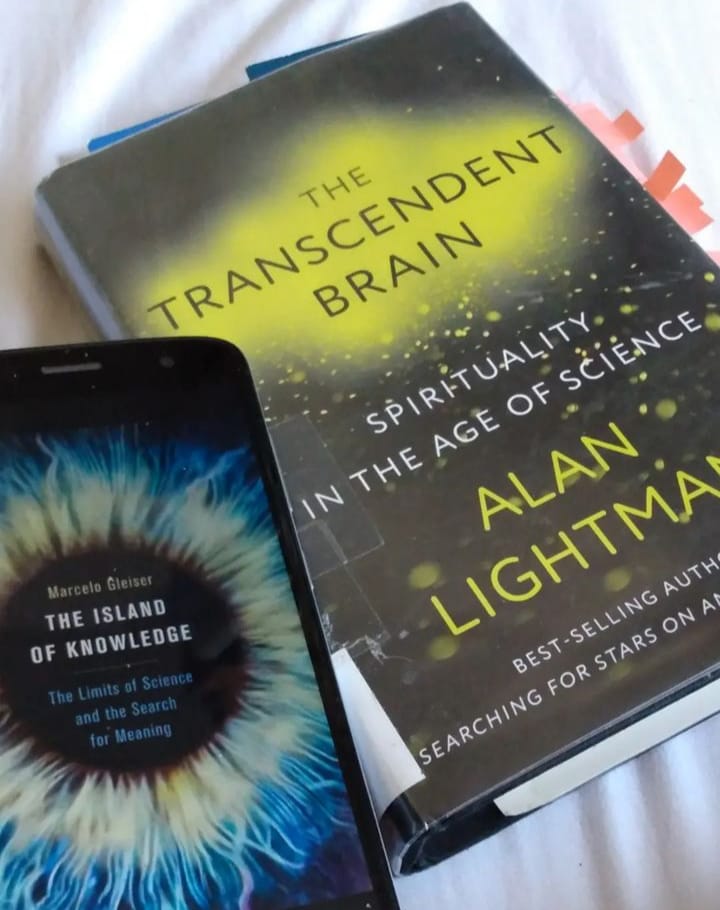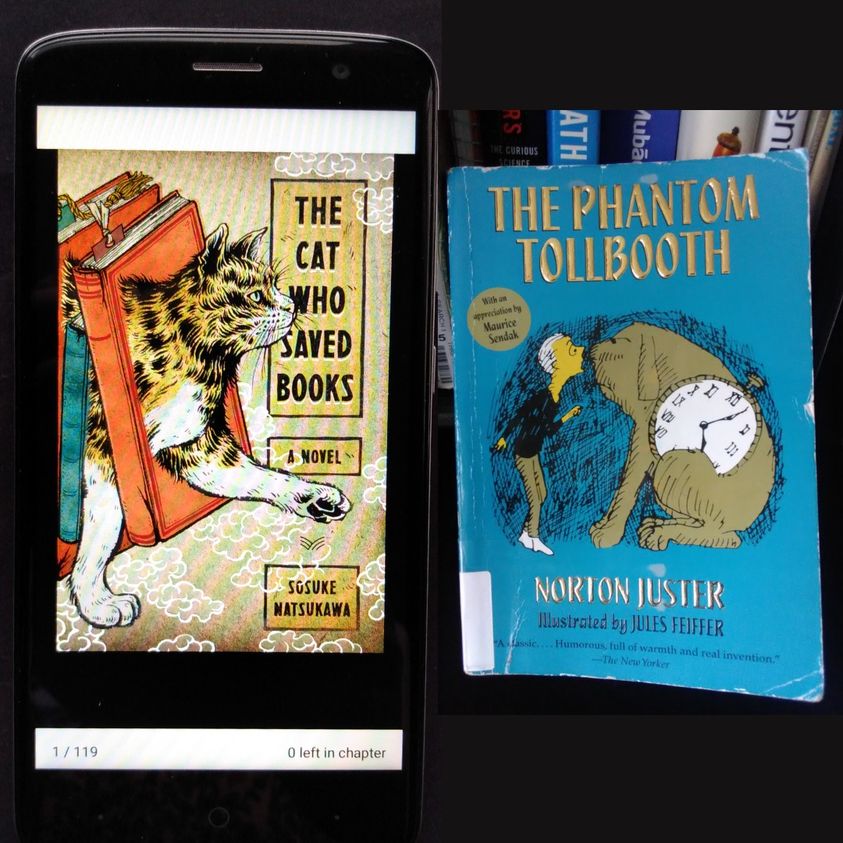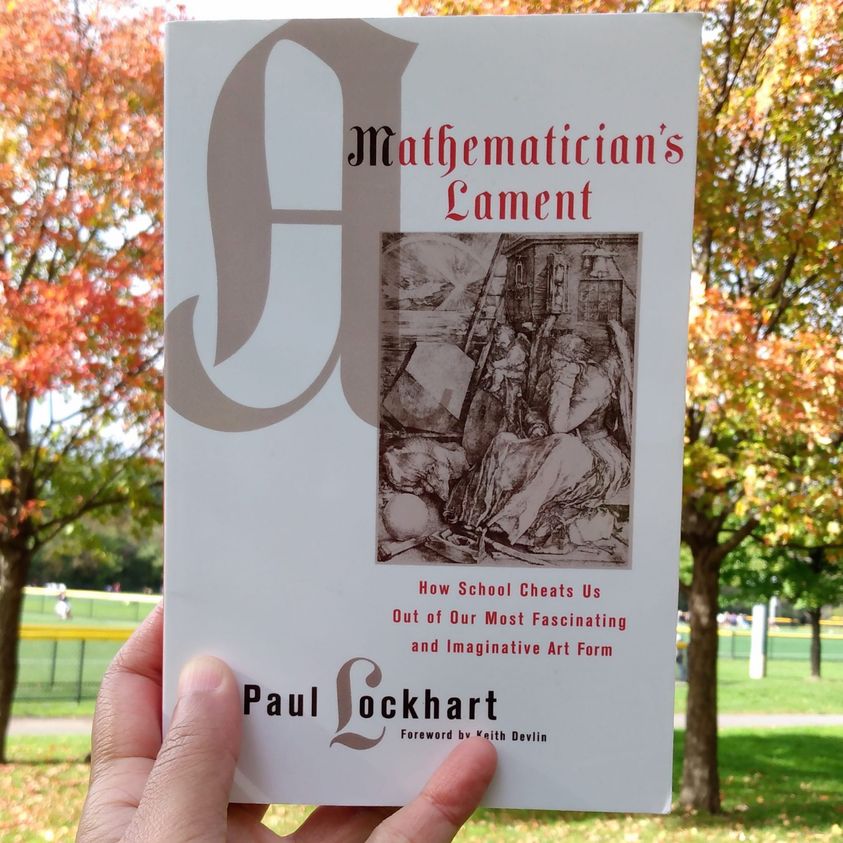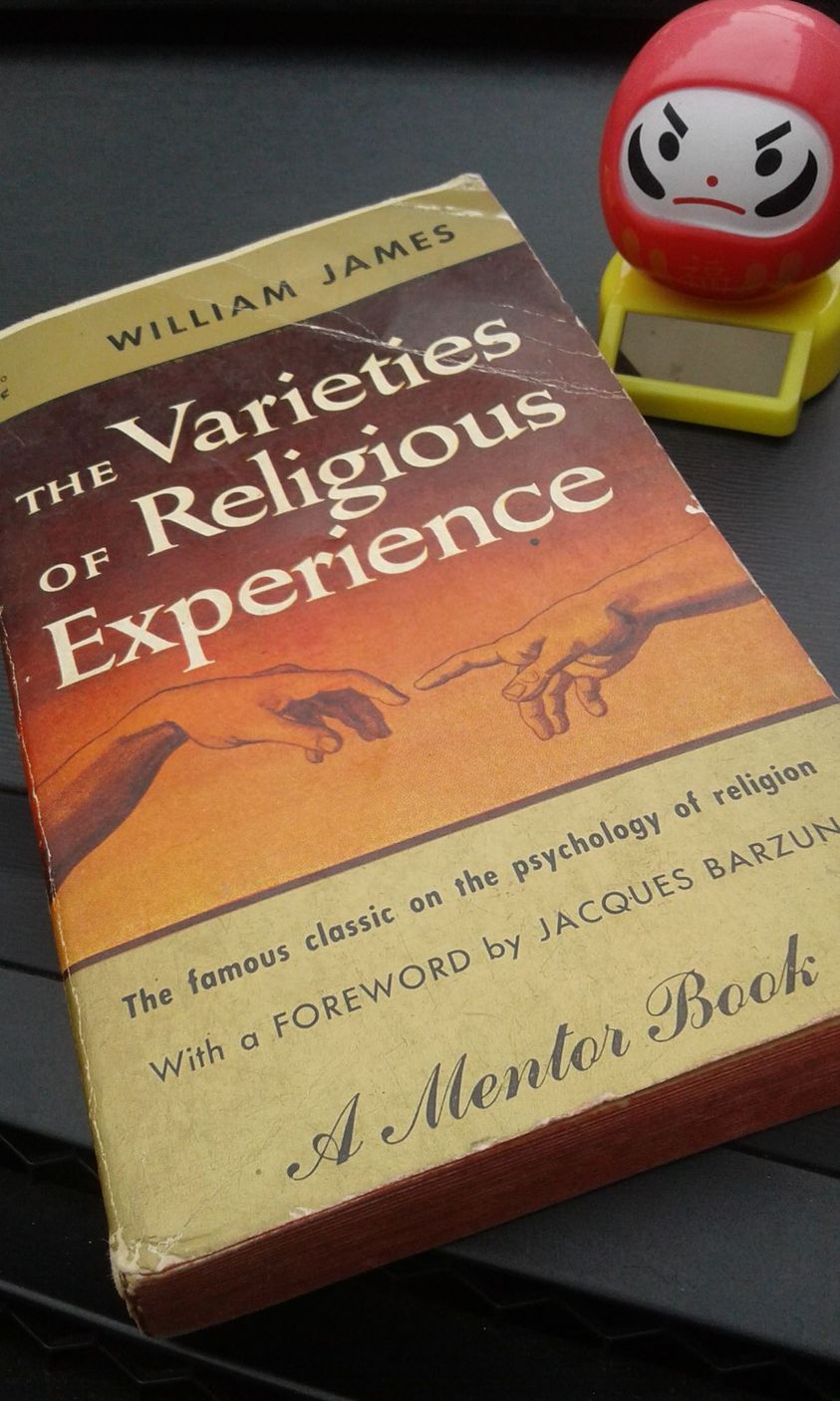Saya pinjam buku ini karena tertarik sama judulnya. Hmm.. spirituality in the age of science? Ini ngebahas apa ya? Ternyata buku ini ditulis oleh seorang fisikawan atheis materialis yang berargumen bahwa spiritualitas bisa muncul (emerge) dari material. Penasaran ya? Yuk kita bahas bukunya.
The Transcendent Brain: Spirituality In The Age of Science
Alan Lightman
Pantheon Books (2023)
194 hal
Alan Lightman adalah astrofisikawan yang sudah berkiprah sebagai pendidik dan periset di dunia akademik selama puluhan tahun di berbagai kampus top di Amerika, termasuk kampus-kampus Ivy League seperti Cornell dan Harvard. Ia salah satu yang pertama memegang jabatan di bidang sains dan humaniora sekaligus di MIT. Lightman mengingatkan saya pada ilmuwan jaman Renaissance yang dibahas di buku Mario Livio kemarin, yang tidak memisah-misahkan antara sains dan humaniora. Selain riset fisika, ia juga menggeluti sastra, filsafat, dan creative writing. Lightman juga salah satu pendiri program science writing di MIT. Sudah puluhan buku baik fiksi maupun nonfiksi yang ditulisnya. Salah satunya, novel Einstein’s Dreams (1993) mendapat banyak pujian di dunia sastra, bahkan menjadi best seller, diterjemahkan ke dalam 30 bahasa, dan diangkat ke panggung teater. Buku The Transcendent Brain adalah bukunya yang terbaru.
Sejak awal buku, Lightman sudah menyebutkan bahwa ia adalah seorang materialis, dalam artian ia menganut kepercayaan bahwa segala sesuatu terbuat dari atom dan molekul, and nothing more. Namun ia juga mengalami pengalaman-pengalaman transenden seperti out-of-body experience, dan pengalaman ‘menyatu dengan alam’, yang seringkali disebut ‘pengalaman spiritual’. Karena itu ia menyebut dirinya ‘spiritual materialist’, dan dalam buku ini ia mengajukan argumen bahwa pengalaman-pengalaman spiritual tadi bisa dijelaskan dari sudut pandang material.
Berbeda dengan buku The World Itself: Consciousness and the Everything of Physics dari atheis materialis Ulf Danielsson yang pernah saya review, buku Lightman terkesan lebih bijak dan rendah hati. Pemakaian kata-kata ‘might’, ‘may be’, ‘I believe’, ‘my thesis’, ‘I claim’, di sepanjang buku, menandakan bahwa Lightman tidak memandang bahwa dia (atau sains) sudah tahu segala jawaban tentang realitas, bahwa yang dia tulis adalan perspektifnya sendiri dan tidak memaksakan pandangannya pada orang lain. “My journey will not be filled with certainties or black-and white pronouncements,” tulisnya. Pemikir yang hati-hati seperti ini adalah angin segar di dunia yang ribut dengan opini.
Dua bab pertama menceritakan sudut pandang dan argumen materialisme mengenai jiwa dan spiritualisme dari pemikir masa lalu (Moses Mendelssohn dan Lucretius), dua bab berikutnya membahas kesadaran dan spiritualisme sebagai emergent dari otak manusia yang kompleks dari ilmuwan modern (neuroscientist Christof Koch dan psikolog Cynthia Frantz).
Di bab ke 3 “Neurons and I”, Lightman membahas bagaimana kesadaran dapat muncul dari otak yang material (catat, Lightman menggunakan kata ‘might arise’, konsisten dengan sikap hati-hatinya). Ia fokus pada otak, namun ia juga mengatakan bahwa kesadaran juga mungkin melibatkan keseluruhan sistem syaraf dan integrasinya dengan keseluruhan tubuh manusia. Menurut Lightman, “mind” dan “brain” adalah sama. Penjabaran argumennya sendiri cukup teknis berdasarkan riset Christof Koch (bisa dicari buku Koch, The Quest for Consciousness), namun intinya adalah bahwa kesadaran muncul dari kerja neuron dan koneksi antara mereka. Di bab ini juga diceritakan ttg “integrated information theory” (IIT) dari neuroscientis Giulio Tononi. Berbeda dengan Koch yang beranggapan bahwa kesadaran mulai dari koneksi neuron di otak, IIT memulai dari pengalaman kesadaran. Ini pernah dibahas di buku Anil Seth, Being You, yang pernah saya review.
Bab 4 membahas bagaimana pengalaman transenden atau spiritualitas, di mana seseorang mengalami ‘satu dengan alam’ bisa terjadi dari sudut pandang psikologi. Ia mengajukan argumen bahwa spiritualitas dapat muncul dari otak melalui jalur kesadaran (sebagai emergent, yg dibahas di bab 3), kecerdasan level tinggi yang dimiliki Homo Sapiens, dan evolusi. Spiritualitas yang ia maksud di sini adalah “the desire for connection and belongin to nature and to other people’ the feeling of being part of something larger than ourselves; the appreciation of beauty; the experience of awe; and the creative transcendent experience”. Menurutnya spiritualitas adalah hal alami bagi manusia, sealami rasa lapar, cinta, dan nafsu, karena semua muncul dari otak manusia yang begitu kompleks. Menurut Lightman, spiritualitas, yang dari sudut pandang evolusi tidak punya keuntungan survival, adalah ‘produk sampingan’ dari sifat-sifat yang punya keuntungan survival. Ia mengajukan konsep “cosmic biocentrism”, rasa persaudaraan dengan semua kehidupan di alam semesta, yang muncul berdasarkan pemahaman sains bahwa kehidupan hanya bisa muncul ‘only during a relatively limited period of time’. Dan karenanya, hidup ini sangat berharga.
Lightman sendiri bercerita bahwa pemahamannya ini beberapa kali diserang oleh para tokoh New Atheist seperti Daniel Dennett dan Richard Dawkins, dianggap membela agama dan ‘pemikiran tidak kritis mereka’. Seperti diketahui, New Atheist menganggap orang beriman sebagai ‘non-thinkers’. Daniel Dennett menyebut pemikirannya ‘fuzzy’ dan tidak kritis pada kepercayaan agama. Lalu kata Lightman, apa dipikir Abraham Lincoln atau Mahatma Gandhi itu ‘fuzzy thinkers’? Ia menyayangkan bahwa sikap seperti itu datang dari tokoh-tokoh sains karena hanya akan memperlebar jurang antar kelompok, alih-alih dialog yang produktif. Lightman sendiri beranggapan bahwa perbedaan pandangan materialis dan non-materialis bukan karena kelompok terakhir ini tidak punya ‘scientific thinking’.
Lightman juga mengkritik mereka yang mencoba menggunakan argumen sains untuk ‘membuktikan bahwa Tuhan tidak ada’ karena hal itu tidak akan pernah bisa dilakukan. “Science can never disprove the existence of God, since God might exist outside the physical universe,” tulisnya (fyi, Richard Dawkins sendiri dalam sebuah wawancara bilang bahwa ‘deist god, the god of physicist and mathematicians’ adalah suatu kemungkinan yang bisa dipertimbangkan, namun ia sendiri menolak menerimanya). Namun Lightman juga mengkritik sikap mengatribusikan segala fenomena kepada Tuhan. “Nor can religion prove the existence of God, since any phenomenon or experience attributed to God might, in principle, find explanation in some nontheist cause,” lanjutnya.
Yang ia tawarkan adalah pandangan bahwa kita bisa menerima sudut pandang saintifik dan pada saat yang sama mengakui bahwa ada fenomena dan pengalaman tertentu yang tidak bisa dijelaskan atau dipahami secara material. (Oya, soal limit sains dibahas secara detail di buku The Island of Knowledge: The Limits of Science and the Search for Meaning dari Marcelo Gleiser yang sedang saya baca dan akan saya review habis ini).
Seperti kata Mario Livio di buku kemarin, konflik antara sains dan agama itu tidak perlu. “We should allow for the coexistence of many ideas and ideals and the freedom to debate those, and disallow only intolerance.” Debat ayo, merendahkan jangan. Sebagai sesama manusia yang ingin memahami dirinya dan kedudukannya di alam semesta, mari kita cari saja kebenaran itu bersama-sama, dalam ketenangan toleransi dan semangat keingintahuan, tanpa saling merendahkan.
-dydy-