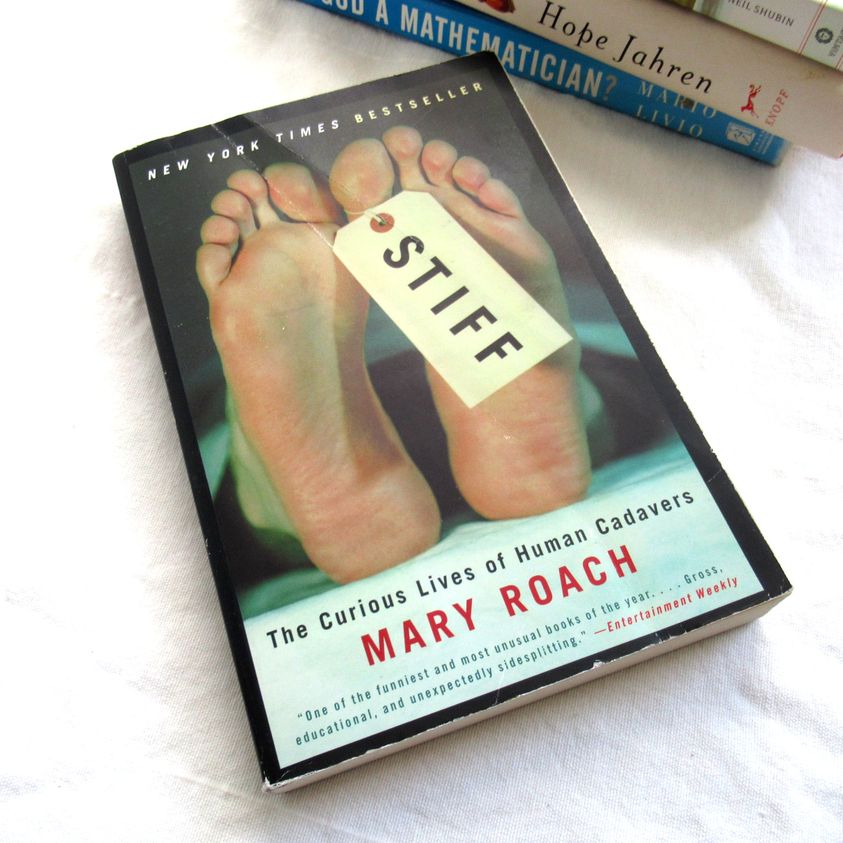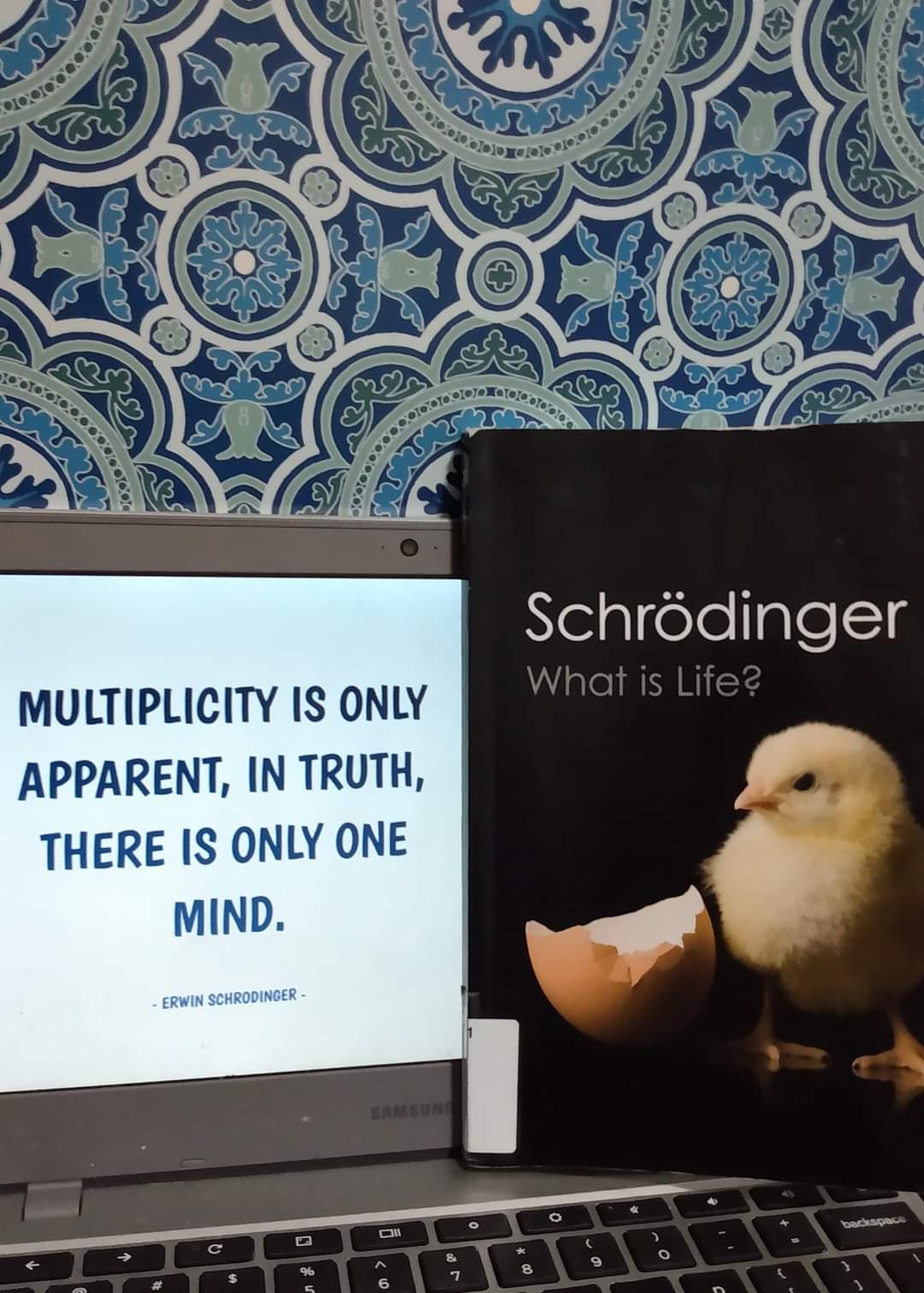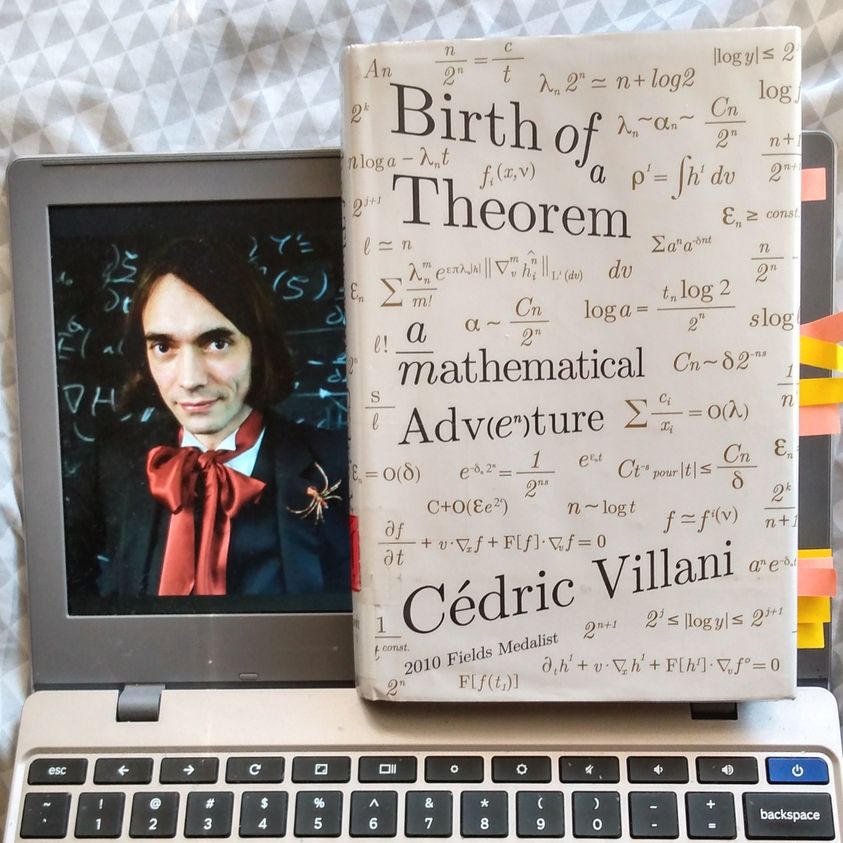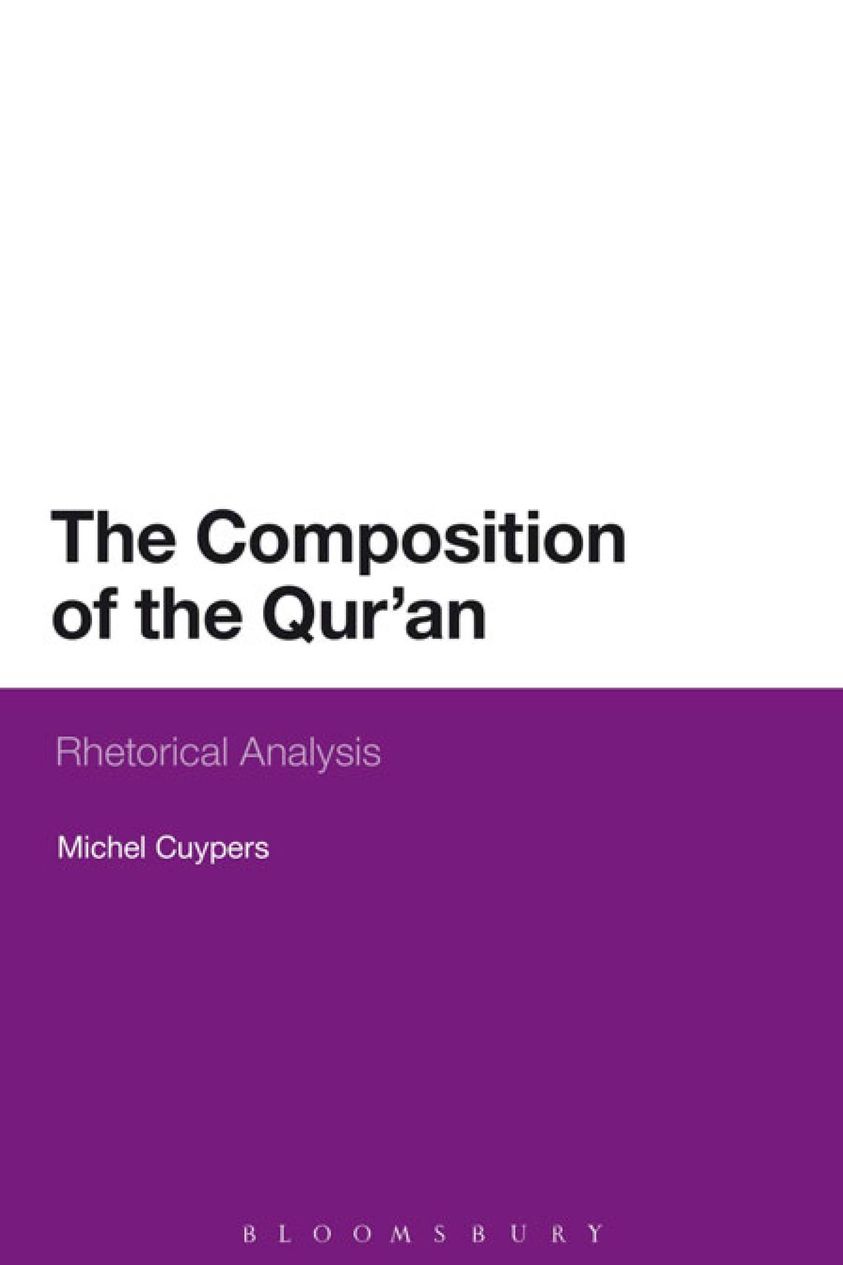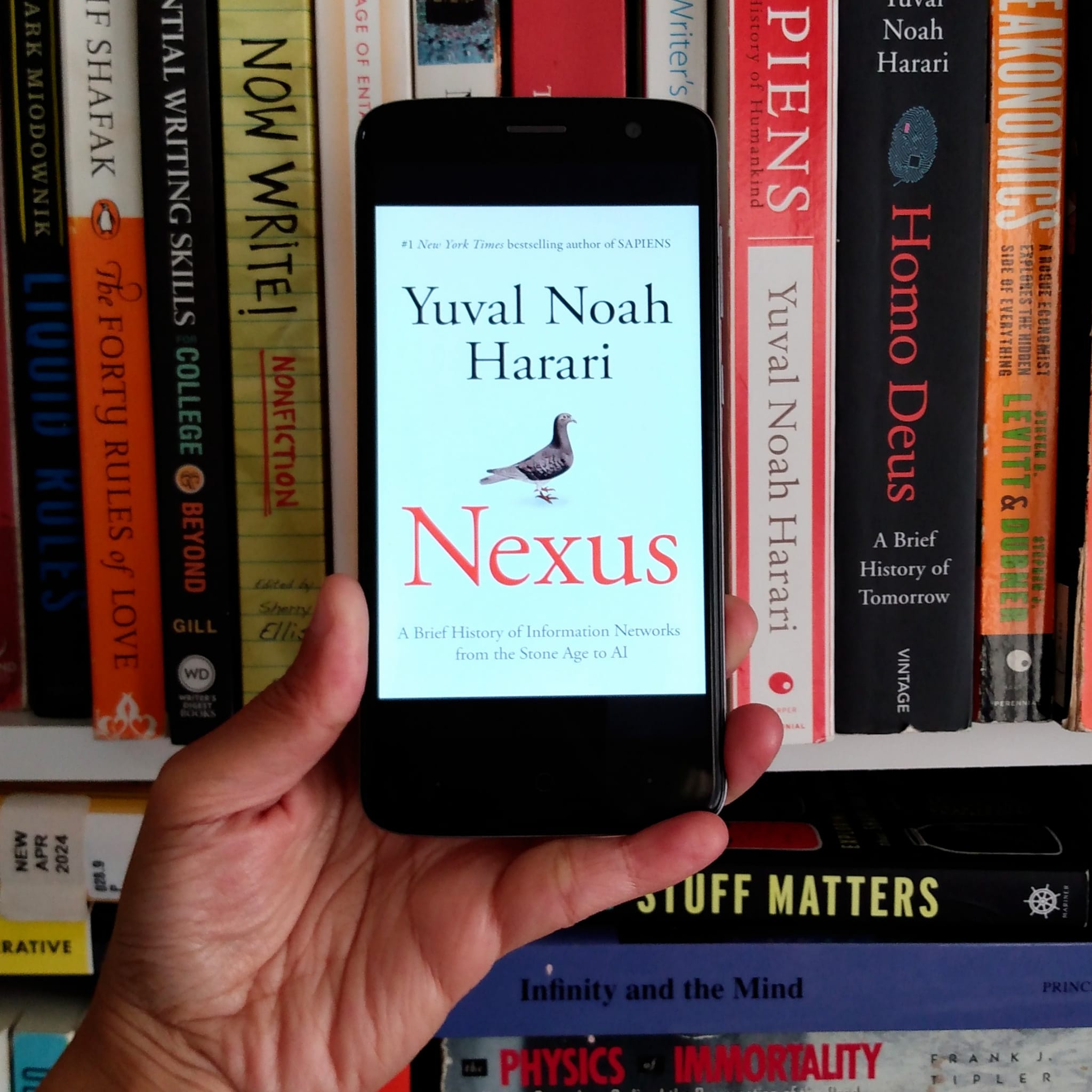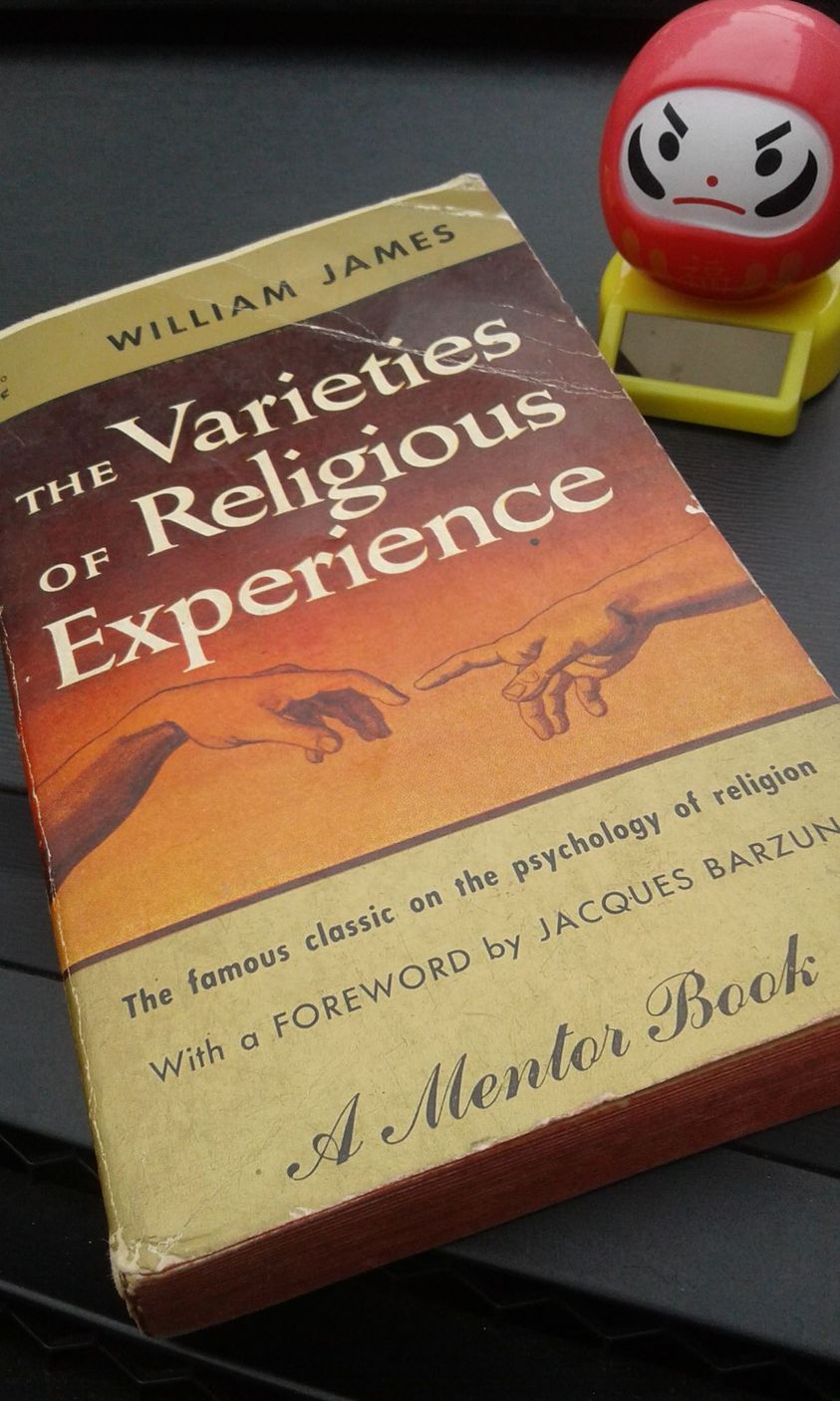“What I see in Nature is a magnificent structure that we can comprehend only very imperfectly, and that must fill a thinking person with a feeling of humility” – Albert Einstein
“What we observe is not Nature itself, but Nature exposed to our method of questioning” – Werner Heisenberg
Seberapa banyak yang bisa manusia ketahui tentang dunia dan alam semesta? Mungkinkah kita mengetahui semuanya? Ataukah ada batas yang tidak bisa dilampaui sains? Jika ya, sejauh mana kita bisa memahami realitas fisik? Melalui buku ini, astrofisikawan Marcelo Gleiser mencoba menjawabnya.
The Island of Knowledge: The Limits of Science and the Search for Meaning
Marcelo Gleiser
Basic Books (2014)
336 hal
Marcelo Gleiser adalah fisikawan dan astronom asal Brazil, profesor fisika dan astronomi di kampus Ivy League Dartmouth College. Saat menulis buku ini sepuluh tahun yg lalu, ia juga adalah Appleton Professor of Natural Philosophy di sana. Seperti Alan Lightman, selain di sains ia juga aktif dalam dialog dengan bidang humaniora. Sebelum buku ini, Gleiser sudah menulis 3 buku lainnya tentang renungan-renungan alam semesta. Ini bukunya yang keempat, dan ia masih terus aktif menulis tentang sains dan budaya. Buku terbarunya The Blind Spot: Why Science Cannot Ignore Human Experience baru saja terbit beberapa bulan lalu.
Saya pinjam buku ini sebetulnya sebagai reaksi dari baca buku The Transcendent Brain. Pas baca buku itu, baru sampai tengah-tengah saya mikir “Kenapa membatasi realitas secara material saja? Why limiting yourself and not open to possibilities?” dan saya teringat buku ini, yang bercerita tentang batas sains. Saya tahu buku ini karena pernah disebut-sebut oleh Marcelo Gleiser di bukunya “The Dawn of A Mindful Universe” yang saya baca dan review beberapa bulan yang lalu. Jadi akhirnya saya baca dua buku ini barengan, yang ternyata saling melengkapi.
Judul buku ini, the Island of Knowledge, adalah sebuah analogi yang mengumpamakan pengetahuan seperti sebuah pulau di tengah samudera yang belum tereksplorasi. Sedikit-sedikit pulau ini meluas, seiring dengan penemuan-penemuan terbaru. Kadang penemuan itu menjadikan batas pulaunya ‘mundur’, karena ide yang dulunya diterima ternyata dipatahkan oleh penemuan yang lebih baru. Kita berharap bahwa dengan semakin banyak hal yang diketahui, maka akan semakin dekat pula kita akan puncak pengetahuan, entah itu Theory of Everything atau ‘the ultimate nature of reality’. Namun, semakin luas ‘pulau’ pengetahuan ini, kalau diperhatikan sebenarnya semakin luas pula ‘pantai’ ketidaktahuan, atau batas antara yang diketahui dan tidak diketahui. Semakin banyak pertanyaan dan misteri.
“As the island of our knowledge grows, so do the shores of our ignorance” – John Wheeler. Cocok sekali dengan peribahasa yang mengatakan bahwa ‘semakin kita tahu, semakin tahu kita bahwa kita tidak tahu’.
Menurut Gleiser, mengambil sudut pandang seperti ini bukanlah sikap menyerah seperti yang dituduhkan banyak orang termasuk sesama ilmuwan sendiri, malah justru membebaskan kita untuk mengeksplorasi, karena begitu banyak misteri yang tersedia dan belum terjawab. Mengekspos batas ilmu pengetahuan ini penting sebagai sikap kritis terhadap diri, ketika arogansi keilmuan begitu merajalela, seolah sains sudah bisa menjawab segala pertanyaan tentang realitas. Mengklaim bahwa kita sudah mengetahui ‘the truth’ itu tidak benar, dan terlalu berat untuk dipikul ilmuwan. “We learn from what we can measure and should be humbled by how much we can’t. It’s what we don’t know that matters,” tulisnya.
Menurut Gleiser, apa yang kita lihat (atau lebih tepatnya ‘deteksi’) di alam semesta hanyalah secuil dari apa yang ada/eksis. Begitu banyak yang tidak terdeteksi, karena seperti juga indera kita, setiap alat pengukuran mempunyai kapasitas yang terbatas. Karenanya Gleiser mengajak kita berhati-hati dengan kata ‘realitas’ sebab bagian besar semesta masih belum bisa kita deteksi. Apa yang kita ketahui sekarang, sebenarnya adalah sebatas ‘apa yang bisa kita ukur dengan teknologi yang tersedia saat ini’, yang menurut Gleiser sih, ‘masih sangat primitif’. Ya, meskipun mungkin bagi kita yang awam ini, sains dan teknologi jaman sekarang itu sudah begitu maju dan modern, namun menurut Gleiser masih terhitung primitif. (Meskipun tidak dibahas di buku ini, tapi fyi, ada yang disebut skala Kardashev yang menjadi ukuran tingkat kemajuan teknologi suatu peradaban berdasarkan besarnya energi yang digunakan. Dan kalau mengacu pada skala ini, memang masih primitif kok. Energi matahari yang berlimpah dan gratisan aja masih belum dimanfaatkan dengan baik)
Teknologi dan metoda ekplorasi baru akan membantu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang sebelumnya bahkan tidak terpikirkan. Ia mencontohkan 2 revolusi sains di abad 17: astronomi sebelum dan sesudah adanya teleskop, atau biologi sebelum dan sesudah ditemukannya mikroskop. Sebelum penemuan teleskop, mempertanyakan benda langit itu seperti apa dan ada apa di permukaannya, sama sekali tidak terpikirkan, karena keliatan juga enggak. Begitu juga makhluk-makhluk renik dalam biologi. Sains belajar dari kegagalan dan kesadaran akan ketidaktahuan. Dengan menyadari ketidaktahuan, barulah kita bisa belajar.
Buku ini terdiri dari 3 bagian besar yang masing-masing terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa bab. Bahasannya mendalam dan banyak yang teknis, tapi tetap mudah diikuti.
Bagian pertama, The Origin of the World and the Nature of the Heavens, membahas kosmos, asal usul dan karakteristik fisikanya, dan bagaimana perkembangan pemahaman manusia tentang tempatnya di alam semesta, dan tentang ruang, waktu, dan energi.
Di bagian ini Gleiser juga mengingatkan ilmuwan bahwa dalam sains pun, kepercayaan (belief) berperan besar dalam eksplorasi sains. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dicek melalui eksperimen, namun melalui ekstrapolasi, dianggap bisa diketahui. Contohnya seperti ‘gravitasi bekerja dengan cara yang sama di segala penjuru semesta’ (ini gimana ngeceknya?), atau ‘teori evolusi melalui seleksi alam berlaku untuk segala bentuk kehidupan termasuk extraterrestrial’ (taunya gimana?). Menurut Gleiser, ini termasuk ‘kepercayaan’. Belum lagi soal batas pengamatan kosmos yang dibatasi oleh cahaya, atau soal multiverse dan parallel universe yang bisa dikategorikan ‘unknowable’.
Bagian kedua, From Alchemy to the Quantum: The Elusive Nature of Reality, membahas evolusi pemahaman manusia tentang karakteristik materi dan komposisinya di alam, dan sejarahnya dari jaman kuno (alchemy) hingga pemikiran masa modern dan bagaimana fisika kuantum membuat kita berpikir ulang tentang realitas dan peran manusia di dalamnya.
Di sini Gleiser mengisahkan perkembangan ilmu pengetahuan sejak jaman kuno tentang atomisme, alchemy, phlogiston, caloric, dll, sebagai pembelajaran (meskipun salah-salah) dalam usaha memahami unsur-unsur pembangun dunia. Ketika dunia kuantum mulai terkuak, manusia dihadapkan pada batas tentang apa yang bisa kita ketahui tentang realitas, dan bagaimana kesadaran mempengaruhi realitas.
Bagian ketiga, Mind and Meaning, mengeksplorasi topik neurosains, kesadaran, komputer, dan matematika, dan bagaimana temuan-temuan di bidang ini berkaitan dengan bahasan tentang limit sains.
Di sini Gleiser antara lain membahas tentang pandangan-pandangan apakah matematika itu ‘alat yang diciptakan manusia’ atau ‘sesuatu yang sudah eksis sebelumnya dan ditemukan oleh manusia’. Sepertinya Gleiser cenderung kepada pandangan ‘diciptakan manusia’ (kebanyakan fisikawan kayaknya begitu deh, tapi sebenarnya banyak matematikawan yang mengatakan bahwa mereka ‘discover mathematics’, bukan ‘invent’. Di antara matematikawan jaman sekarang yang berpendapat seperti ini misalnya Roger Penrose, Terence Tao, dan Steven Strogatz). Namun, bagi Gleiser, pandangan bahwa matematika itu diciptakan oleh manusia mengandung arti bahwa kebenaran matematika itu tidak ada ‘di luar sana’, melainkan di dalam diri kita, karena merupakan produk pemikiran otak manusia yang istimewa.
Gleiser juga mengangkat secara singkat Teorema Ketidaklengkapan Godel dan Turing halting problem, yang menunjukkan bahwa ada realitas yang ‘unknowable’ bahkan dalam matematika pun. Bagi Gleiser, temuan ini merupakan kebebasan. “How refreshing that we are not slaves to a formal intellectual process…Incompleteness leads to creative freedom,” tulisnya. Hal ini justru seharusnya menjadi pendorong bagi para ilmuwan untuk terus bertanya, mencari jawaban.
“Science is a response to our urge to understand, to make sense of the world we live in and our place in it. We may crave certainty but must embrace uncertainty in order to grow. We are surrounded by horizons, by incompleteness.”
“We push the limits and keep on pushing so that we can better know who we are. The day we become too afraid to step into the unknown is the day we stop growing.”
-dydy-