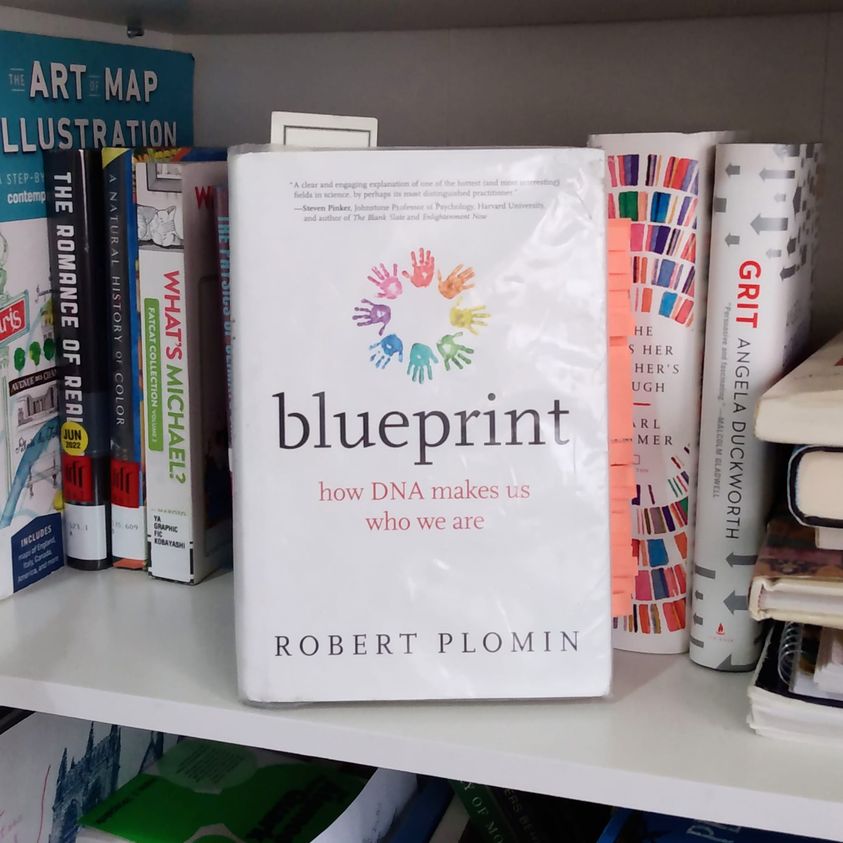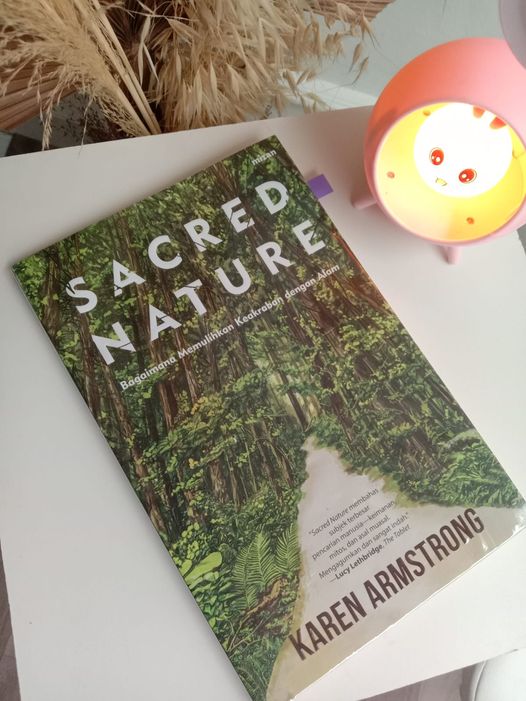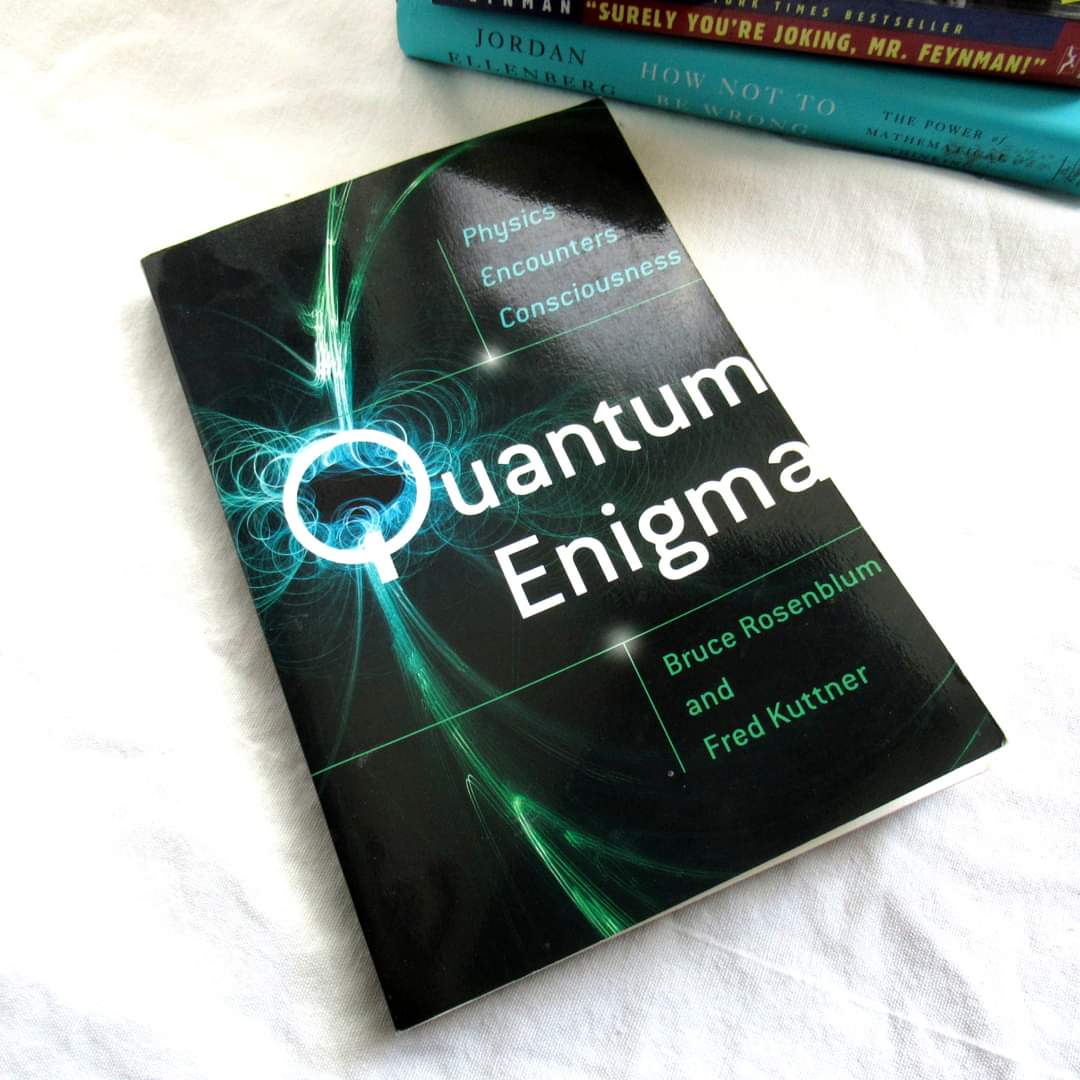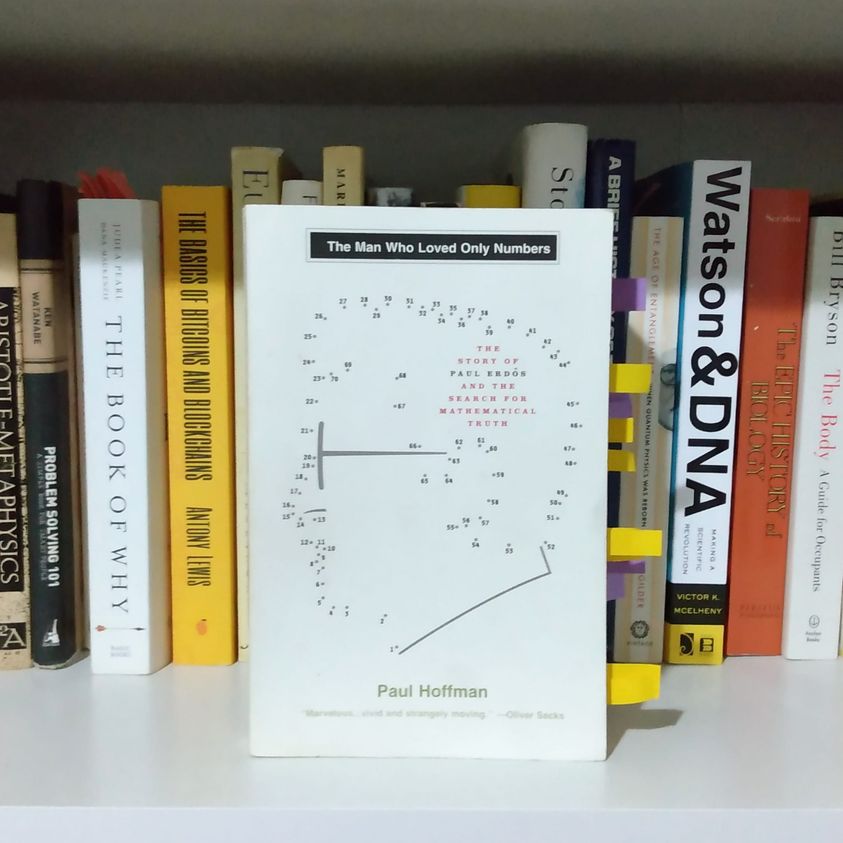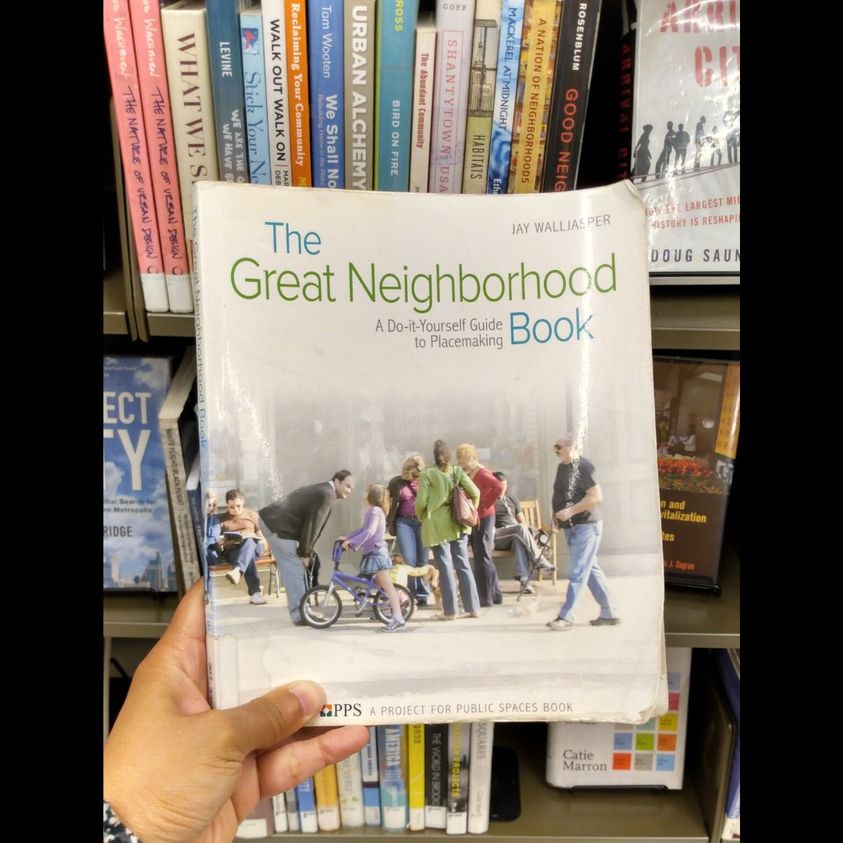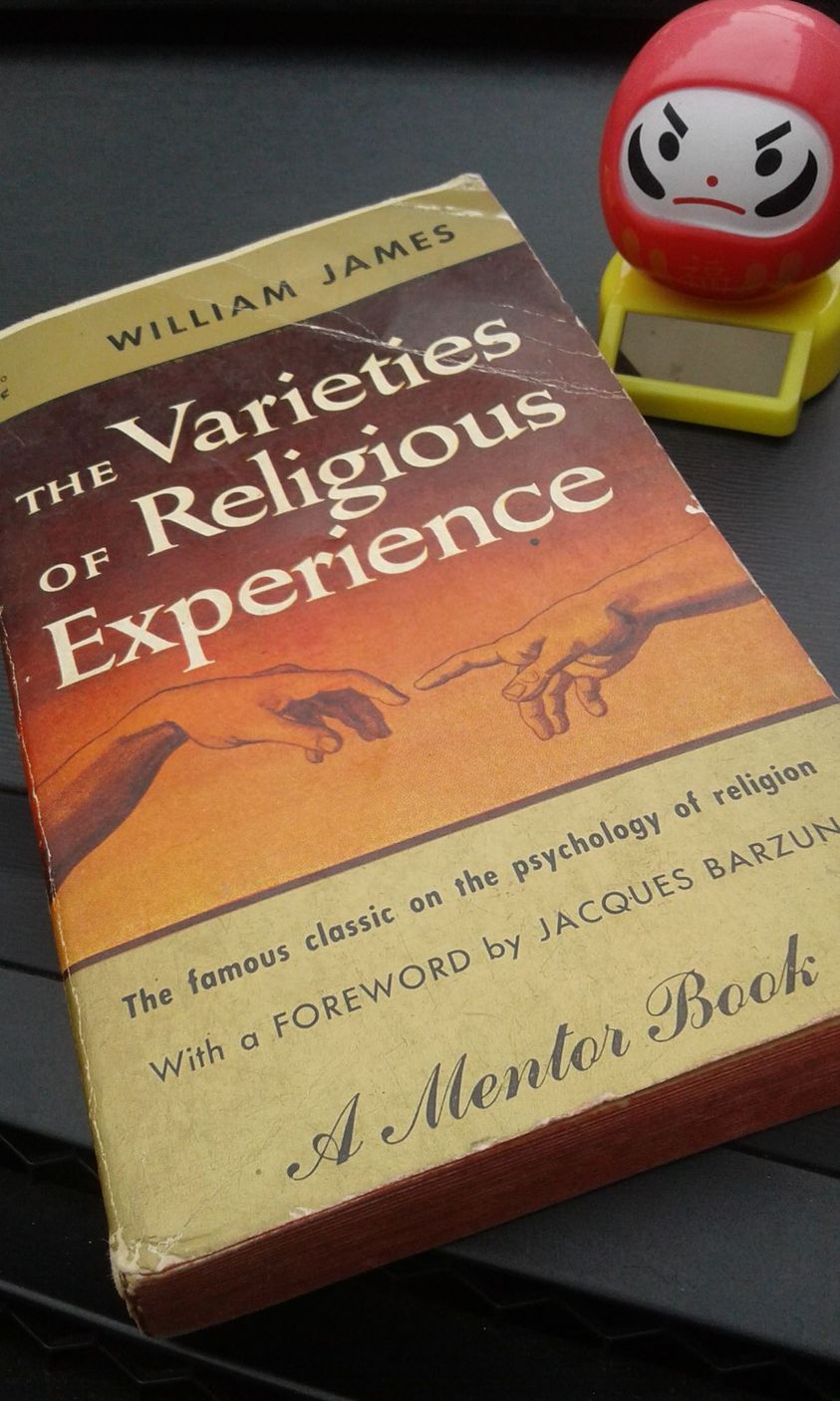Mana yang lebih berpengaruh terhadap kepribadian kita, nature atau nurture? Apakah sekolah favorit bagus karena kualitas sekolahnya yang bagus, atau karena memang isinya anak-anak yang sudah pintar dari sananya? Bisakah kita memprediksi kepribadian seorang bayi dari sekuens genomnya? Penasaran kan?
Buku ini membahas bagaimana kemajuan teknologi DNA sequencing telah banyak membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.
Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are
Robert Plomin
MIT Press (2018)
279 hal
Robert Plomin adalah profesor behavioral genetics di King’s College, London. Ia seorang peneliti senior yang sudah melakukan riset tentang behavior genetics dari 40an tahun yang lalu, mencoba meng’ekstrak’ perbedaan genotype-phenotype antar individu melalui studi orang kembar. Karena risetnya ini ia mendapat penghargaan dari pemerintah Inggris.
Sebetulnya buku ini bikin frustrasi, karena susunan dan cara penulisannya sangat…hmmm.. memusingkan, muter-muter dan kalimat-kalimat yang persis diulang-ulang terus. Aneh karena di sampulnya ada testimoni Steven Pinker yg bilang ‘a clear and engaging explanation from its most distinguished practicioner’. Masa linguist nggak ngeh sama tulisan muter-muter begini.
Mungkin karena Plomin ilmuwan behavioral genetics senior ya, dan temuannya memang penting, jadi pada segan.
Buku Genetic Lottery dari Kathryn Harden mengemas ulang isi buku ini secara lebih fasih dan teratur, dan menyampaikan inti dari pentingnya studi behavioral genetics yang telah dilakukan oleh Robert Plomin dkk. (fiuh, untung saya baca buku Harden duluan)
Ok, jadi di review ini saya mencoba rephrase dalam bahasa sederhana apa yang diceritakan oleh Robert Plomin di buku ini.
Riset yang dilakukan Plomin bertujuan mengidentifikasi apa persisnya yang membuat kepribadian dan psikis seorang individu berbeda dengan individu lainnya. Misalnya, kenapa kok saudara sedarah bisa berbeda sifat secara ekstrim padahal berasal dari orang tua yang sama? Sebelum genetika mulai diperhitungkan, fenomena ini merupakan salah satu teka-teki dunia psikologi. Dia mulai penelitian ini ketika ilmu genetika mulai bisa melakukan DNA sequencing meskipun masih sulit dan sangat mahal. Metoda yang dilakukan adalah melalui studi orang kembar terutama kembar identik (karena mereka berasal dari gen yang sama) dan membandingkannya dengan kembar fraternal dan saudara sedarah (siblings). Selain itu juga meneliti kembar identik yang dipisahkan sejak bayi, dan bayi yang diadopsi, untuk membandingkan pengaruh nature vs nurture.
Dalam penelitiannya ia mengikuti perkembangan anak kembar sejak lahir hingga dewasa. Beberapa temuan dari penelitian ini di antaranya adalah:
1. Dalam banyak hal (termasuk yg berkaitan dengan psikis), genetiklah yang lebih besar pengaruhnya dibanding lingkungan. Anak yang diadopsi, meskipun mendapatkan nurture yang sama dari satu keluarga, namun dalam banyak hal (termasuk berat badan dan pencapaian akademik) tetap lebih mirip dengan karakteristik fisik, kepribadian, dan pencapaian akademik orang tua biologisnya. Kesimpulannya, mau hidup di lingkungan manapun, genetiklah yang berpengaruh lebih besar terhadap kepribadian seseorang.
Ada kasus notorious di New York di mana kembar tiga sengaja dipisahkan dari bayi dan ditempatkan di keluarga adopsi dengan kelas ekonomi berbeda, namun tanpa sengaja mereka bertemu di jaman kuliah. Mereka ternyata dijadikan kelinci percobaan oleh seorang psikiater (bukan Plomin tentunya). Selain fisik dan sifat yang sama meskipun dibesarkan di lingkungan berbeda sejak lahir, mereka pun sama-sama memiliki kecenderungan depresi, bahkan salah satunya akhirnya bunuh diri (silakan dicari film dokumenternya Three Identical Strangers, 2018)
2. Pengaruh genetik sangat besar pada kondisi psikologis, selain untuk hal-hal yang sudah diduga seperti schizophrenia (50%) dan autisme (70%), namun juga untuk hal-hal seperti general intelligence (50%), kesulitan membaca (60%), pencapaian akademik (60%), kemampuan verbal (60%), kemampuan spasial (70%), mengenali wajah (60%), bahkan kepribadian (40%).
Selama ini umumnya kita mengira untuk hal-hal seperti ini lingkungan dan pola asuh yang pengaruhnya besar, tapi Plomin mengingatkan bahwa “Life experiences are not something that is passively happen to us”. Bagaimana kita merespon dan mempersepsi pengalaman itu tergantung kecenderungan genetik kita. Lingkungan dan pengalaman hidup yang sama akan memberi efek yang berbeda bagi orang yang optimis vs yang cenderung gampang stress, misalnya.
Sebelumnya, ilmu psikologi biasanya mengabaikan faktor genetik dan lebih fokus ke faktor lingkungan sebagai pengaruh utama. Misal: seorang anak yang ibunya rajin membacakan buku akan tumbuh menjadi anak yang pencapaian akademiknya bagus di sekolah. Padahal menurut Plomin, dalam kegiatan membaca buku itu ada pengaruh genetik yang besar: memang ibu dan anaknya sama-sama kemampuan kognitifnya tinggi, misalnya. Jadi pencapaian akademik di sekolah sangat mungkin karena memang anaknya pintar dari sananya, bukan karena dibacakan buku. Hal seperti ini biasanya tidak diperhitungkan dalam riset psikologi (ini kata pak Plomin sendiri lho ya, bukan kata saya, kalau-kalau ada psikolog yang protes).
Dengan perkembangan teknologi genetik dan DNA sequencing, sekarang metoda yang dipakai untuk memprediksi pengaruh genetik terhadap resiko penyakit, sifat atau karakter dilakukan dengan Genome Wide Association Study (GWAS) untuk menemukan SNP (Single Nucleotide Polymorphism) tertentu, kemudian informasi itu digunakan untuk merumuskan polygenic score yang berkorelasi dengan sifat/fenomena tertentu.
Sebelumnya perlu dijelaskan SNP itu seperti ini: jika misalnya pada umumnya posisi genom tertentu memiliki nukleotid A, eh ternyata si X di posisi yang sama memiliki nukleotid T, si Y memiliki nukleotid C, sementara si Z memiliki nukleotid G. Perbedaan genotype ini menghasilkan fungsi yang berbeda, dan diekspresikan secara berbeda pula. Polymorph berarti ‘banyak bentuk’.
Polygenic score ini, seperti namanya, bukan korelasi one-to-one. Bukan satu gen menghasilkan satu sifat. Polygenic score terdiri dari puluhan, ratusan, atau ribuan SNP. Malah untuk fenomena kompleks seperti ‘general intelligence’ atau ‘pencapaian akademik’ diperlukan puluhan ribu SNP yang meskipun efek masing-masingnya kecil, tapi gabungan semuanya menghasilkan perbedaan yang signifikan.
Studi-studi asosiasi genotype-phenotype ini juga sangat ketat dalam soal jumlah sampel, karena polanya baru akan muncul jika sampelnya sangat besar (sementara riset psikologi seringkali sampelnya terlalu sedikit). Dengan kata lain, polanya baru terlihat ketika dizoom-out. Menurut Plomin, metoda GWAS akan mengubah besar-besaran ilmu psikologi.
Polygenic score ini sudah mulai digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menawarkan genetic testing untuk menganalisa resiko kesehatan, misalnya. Tetapi menurut Plomin polygenic score tidak hanya berguna untuk identifikasi resiko penyakit, melainkan juga untuk berbagai fenomena lainnya. Predictive powernya besar! Dengan menganalisa polygenic score yang berkaitan dengan ketinggian, seorang bayi bisa diprediksi apakah setelah dewasa dia akan tinggi atau pendek, bahkan tanpa mengetahui apakah orang tuanya tinggi atau pendek.
Temuan lain dari riset Plomin ini adalah bahwa semua karakteristik psikologis ini terdistribusi secara sempurna dalam bentuk bell curve. Jadi tidak tepat suatu fenomena disebut ‘disorder’, lebih tepat dia adalah outlier dari normal distribution. Rata-rata orang punya secuil SNP yang berkaitan dengan fenomena-fenomena psikologis yang biasanya dikaitkan dengan ‘disorder’ tadi, namun levelnyalah yang berbeda-beda, sehingga ekspresinya bisa muncul di luar atau tidak. Kalau seperti ini, pantaskah disebut disorder? Plomin mengajak kalangan psikologi untuk mulai meninggalkan paradigma ‘disorder’ dan beralih ke ‘dimension’ atau spektrum.
Apa hikmah dari sini? Dengan mengetahui bahwa semua kondisi ini dipengaruhi genetik, maka kita tidak bisa terlalu mudah menyalahkan dan judgmental terhadap orang lain yang, misalnya, mudah depresi, lambat belajar, atau kegemukan, atau apa saja. “Hikmahnya adalah toleransi.” Plomin sendiri polygenic score untuk berat badannya tinggi, punya resiko tinggi obesitas, yang berarti berat badannya lebih mudah naik dan lebih sulit turun dibanding mereka yang skornya rendah. Jadi kalau ada yang gemuk jangan langsung dibilang “Kamu sih nggak mau diet”. Bisa jadi bukan nggak mau, tapi sudah berkali-kali diet pun beratnya nggak turun-turun. Informasi ini juga bisa digunakan oleh yang bersangkutan untuk, misalnya, lebih berhati-hati memilih makanan, tidak menimbun snack di tempat yang mudah diraih, lebih rajin berolahraga dll dsb.
Selain ‘jangan mudah menyalahkan orang lain’, hikmah lainnya juga adalah ‘jangan mudah menyalahkan diri sendiri’ alias ikhlas menerima kelebihan dan kekurangan diri. Kita digariskan memiliki DNA seperti ini, apakah mau protes? Atau menjalankan sesuai potensinya?
Setelah direnung-renungkan, soal genetik ini mengingatkan saya tentang buku Karma dari Sadhguru. Kenapa? Karena gen bersifat seperti karma yang dijelaskan di buku itu: mencengkeram sangat kuat, kita tidak bisa lepas dari ‘trajectory’ yang sudah dituliskan di dalamnya. Meskipun lingkungan mempengaruhi, tapi pengaruhnya tidak langgeng, sistematik dan berkelanjutan. Dan karma ini terus ‘hidup’ karena diwariskan kepada keturunan kita.
Buat saya pribadi ini jadi berkaitan erat dengan ajaran agama. Dalam agama ditunjukkan nilai-nilai yang ‘baik’ dan seharusnya menjadi aspirasi. Perintah-perintah dalam agama itu menjadi semacam tips & trik untuk membantu kita mengikis cengkeraman genetik (karma?), dengan belajar menahan diri. Lihat saja perintah solat dan puasa, itu latihan ‘menaklukkan’ diri, melatih kedisiplinan, mengontrol impuls (self discipline ini disinggung juga di buku Gary Nabhan, tentang makan dan gaya hidup yang sesuai dengan tubuh masing-masing). Bahkan dalam penelitian-penelitian terbaru tentang puasa dan meditasi, hal-hal tsb memang besar pengaruhnya terhadap kerja sel (ada buku-buku ilmiah tentang ini tapi belum saya baca: Altered Traits dari Daniel Goleman ttg meditasi, Lifespan dari David Sinclair ttg penuaan tapi juga membahas ttg manfaat besar puasa dalam kesehatan sel).
Sadar kalau kita susah fokus? Jangan menyerah dengan ‘ah memang aku gennya gitu’, karena ada tips & trik untuk membantunya. Contohnya disiplin membatasi distraksi, memakai alat bantu seperti scheduling, reminder. Sadar kalau kita gampang ‘kebawa-bawa’? Tipsnya jauhi godaan dan pengaruh buruk yang akan ‘menjatuhkan’ kita dan menjauhkan kita dari ‘the ideal’.
Memang susah ya, kan memang perang paling berat itu perang melawan diri sendiri. Tapi kita perlu kenal dulu sama diri sendiri, supaya perangnya efektif dan efisien tidak salah sasaran. Dan ilmu genetik lewat DNA sequencing dan polygenic score bisa membantu kita lebih mengenal diri, dan, jika ada kekurangan bisa intervensi lebih cepat.