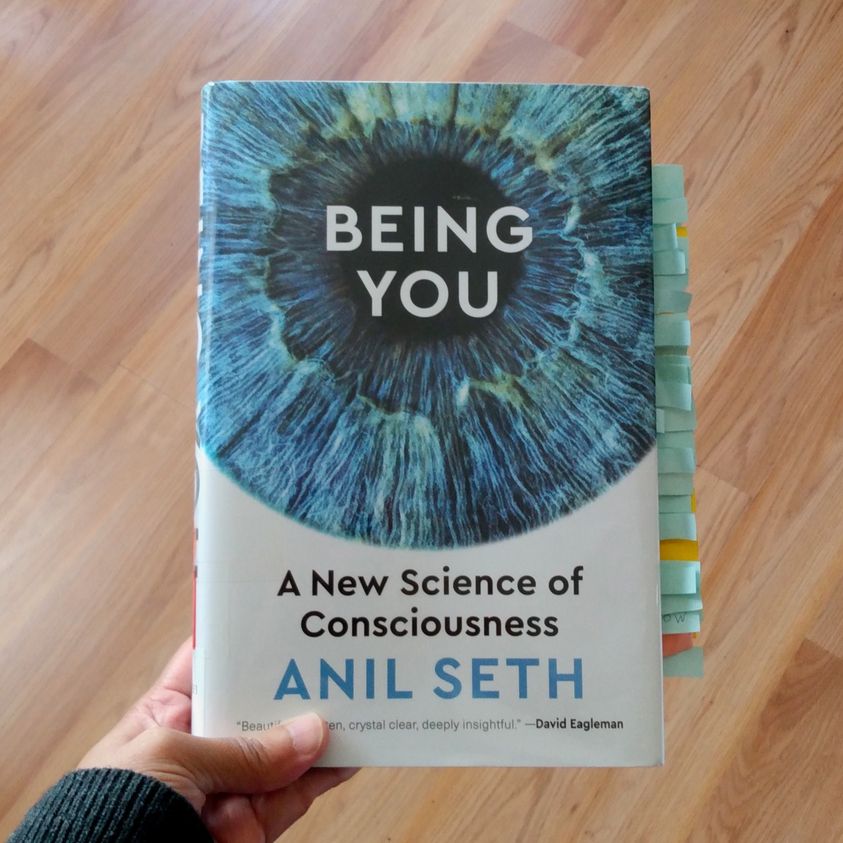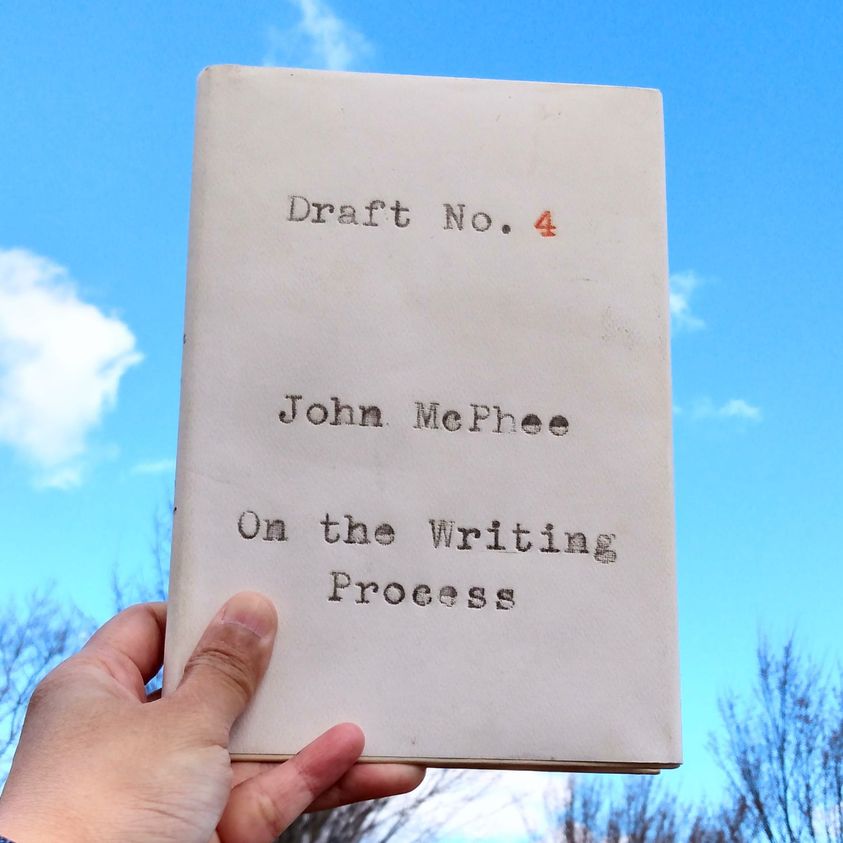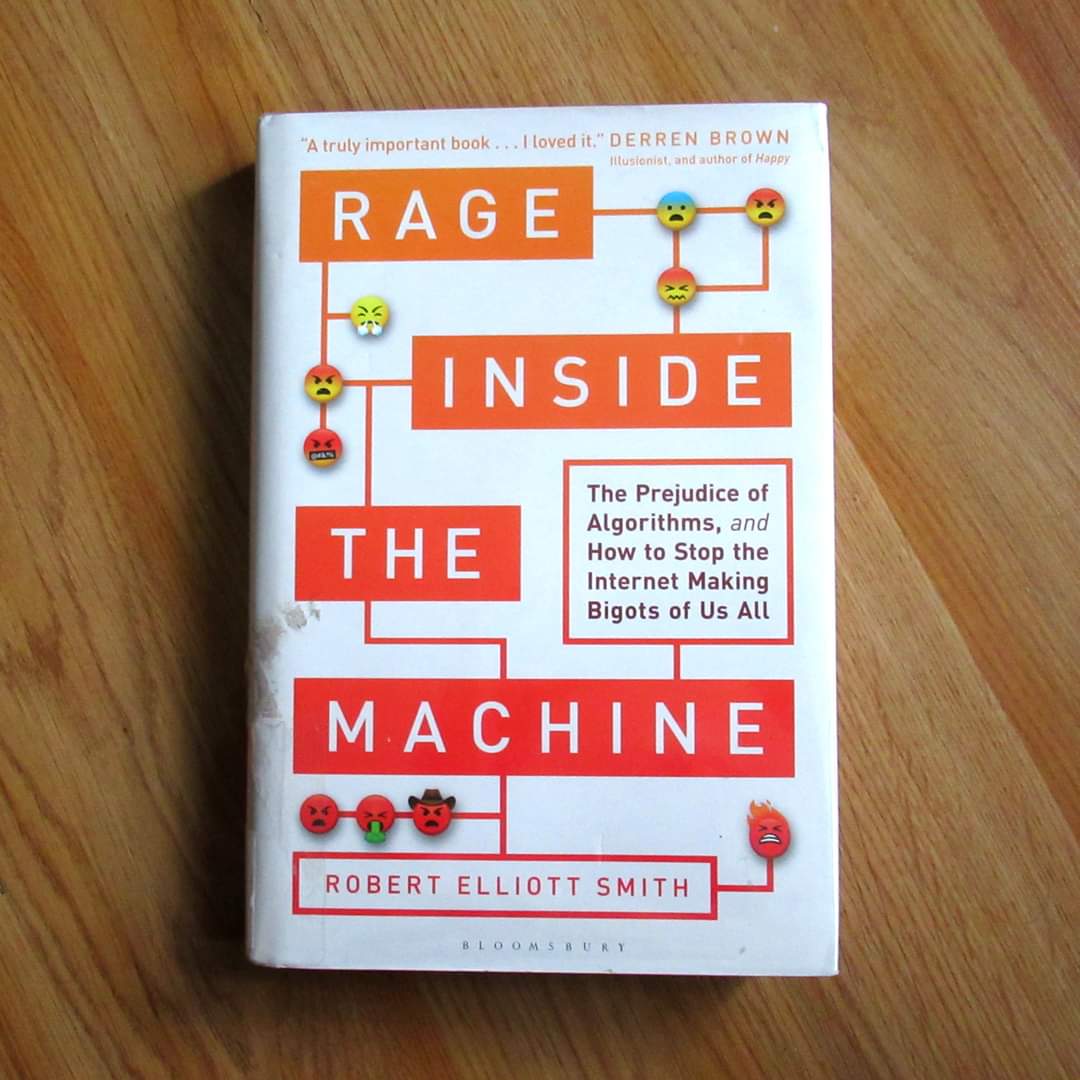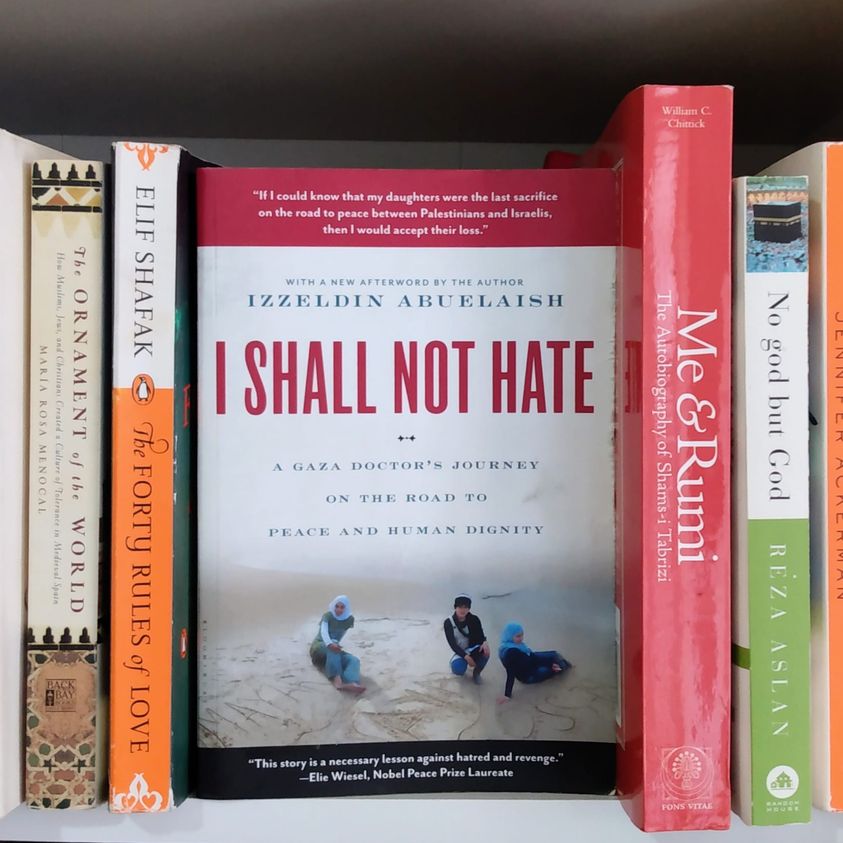Mengapa di Indonesia, korupsi-kolusi-nepotisme sangat sulit diberantas? Mengapa orang Indonesia gemar sekali kepo pada orang lain: ‘Dari mana? Agamamu apa? Sudah nikah belum?’
Mengapa ibu-ibu gemar sekali pakai baju dress code seragaman? Mengapa profesi PNS diburu? Mengapa demokrasi Indonesia diterjemahkan sebagai demo (untuk) nasi?
Jawaban dari semua ini terangkum dalam buku yang ditulis sesuai dengan gaya penulisnya: santai, kocak, penuh semangat, dan… terjungkir-balik jatuh cinta dengan negara ajaib ini.
Indonesia Etc, Exploring The Improbable Nation
Elizabeth Pisani
Granta Publication, London, 2014
403 halaman
Elizabeth Pisani menganggap Indonesia seperti bad boyfriend, pacar nyebelin yang sekaligus ngangenin. Sejak ditempatkan di Indonesia sebagai koresponden Reuters tahun 1988, Pisani sudah berkali-kali mengunjungi Indonesia dalam berbagai tugas. Dia termasuk sedikit dari wartawan asing yang dibolehkan masuk Aceh pada masa konflik, berteman dengan cukup banyak pejabat publik, bergaul dengan berbagai kalangan dari seluruh Indonesia, dan juga sempat menyaksikan pemilu Jakarta tahun 2012. Dia memutuskan menulis buku ini setelah berkeliling Indonesia tahun 2011, sebuah cerita tentang negeri yang disebutnya ‘Improbable Nation’, negara ajaib penuh keanehan, termasuk ‘aneh, kok bisa ada!’
Terus terang buku ini sulit untuk direview, karena banyak sekali hal menarik yang diceritakan. Pisani mengelilingi Indonesia dengan metode yang ‘sangat Indonesia’: asal jalan ke terminal atau pelabuhan, mengobrol dengan orang-orang, dan selalu akan ada orang yang mengajaknya ikut serta. ‘Miss, ayo ikut ke rumah saya di Sumba!’. ‘Miss, ayo menginap di rumah saya di Halmahera!’ . ‘Miss, sebentar lagi kami mengadakan pesta pernikahan keponakan, tinggallah di tempat kami sebentar!’. Pisani sangat mengagumi keramahan dan ketulusan orang Indonesia. Pisani sendiri akhirnya menyadari bahwa dia sudah jadi ‘Indonesia’ saat mengobrol dengan seorang perempuan cantik kosmopolitan khas Jakarta. Si cantik terheran-heran mendengar Pisani baru datang dari Sangihe. ‘Di mana itu?’ tanya Si Cantik. Sebaliknya, Pisani tersadar kalau Si Cantik, yang asli Indonesia itu, mungkin lebih akrab dengan nama jalan di Paris daripada Sangihe.
Berbekal jiwa petualang dan pergaulannya yang luas, Pisani mencoba mencatat hal-hal unik yang membuat Indonesia jadi ‘Indonesia’ seperti sekarang ini. Misalnya, kegilaan orang Indonesia pada jabatan PNS dan gaya baju seragam. Hal itu bermula dari zaman penjajahan Belanda, saat PNS menjadi profesi yang dihormati dan bisa memiliki sedikit kekuasaan. Gaji PNS tidak banyak, tapi menjanjikan kestabilan dalam badai ekonomi yang hampir selalu melanda Indonesia sejak masa penjajahan. Seragam menjadi simbol status, karena itu tanpa sadar orang Indonesia sangat suka dengan seragam. Kata Pisani, nyaris tidak mungkin ada semacam perkumpulan tanpa ada seragam. Seragam juga menguatkan nilai komunal yang berakar sangat dalam di jiwa orang Indonesia. Individualisme ala Eropa adalah hal yang asing dan baru-baru saja diadopsi dalam kultur manusia Indonesia, itupun baru oleh segelintir masyarakat berpendidikan tinggi.
Karena kultur komunal ini jugalah, korupsi-kolusi-nepotisme sangat sulit diberantas. Demokrasi Barat diasumsikan dibangun atas individu-individu merdeka yang memiliki akses informasi yang sama, sehingga bisa memutuskan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, ikatan klan/keluarga besar sangat kuat. Orang-orang yang sukses dalam keluarga besar diharapkan mengembalikan bakti pada keluarga. Jika tidak berupa uang, ya berupa kemudahan-kemudahan pendapatan maupun pekerjaan. Keluarga Besar bisa mencakup keluarga sedarah, bisa juga meluas menjadi penduduk satu daerah. Bagi kebanyakan orang, meminta bantuan ‘paman anggota DPRD’ untuk memuluskan penerimaan PNS keponakan, bukan termasuk KKN. Itu adalah timbal balik wajar karena kesuksesan individu dianggap sebagai hasil dari kontribusi keluarga besar. Jangankan mencegah diri dari KKN, memahami konsep bahwa KKN dilarang saja sulit!
Demokrasi di Indonesia menjadi ‘aneh’ karena konsepnya berusaha diterapkan untuk masyarakat yang terbiasa ‘manut apa kata Bapak’, ‘menunggu petunjuk Bapak’. ‘Bapak’ di sini bisa bapak formal (kepala pemerintahan setempat) atau bapak informal (para pemuka adat, pemuka agama, atau sekadar dituakan). Satu-satunya hal yang menarik dari demokrasi ala pemilihan langsung adalah terbukanya ‘industri demo’. Sejak tekanan Orba hilang, demo sudah jadi komoditas tersendiri, lengkap dengan koordinator demo pembawa massa, poster-poster siap angkat, katering logistik, penyewaan mobil angkutan, kaos seragam, serta ‘pasukan keamanan’. Para pembawa massa juga bisa disewa untuk ‘mendukung demokrasi’ dengan cara meramaikan kampanye pemilu. Bahkan ada harga tersendiri untuk sengaja parkir mobil sembarangan agar lokasi kampanye terlihat ramai karena jalanan macet. Di daerah-daerah tambang, industri demo kadang menjadi satu-satunya sumber pendapatan rakyat sekitar, karena mereka tidak memiliki cukup keahlian untuk direkrut oleh perusahaan tambang. Ajaib? Miris? Ya begitulah.
Kata ‘Ya begitulah’ seringkali muncul di buku ini. Pisani berkeliling Indonesia tahun 2011, saat Jakarta sang Ibukota sekalipun belum punya sistem angkutan umum yang memadai. Kapal feri telat 13 jam? Ya begitulah. Pesawat baru akan datang satu bulan lagi ke pulau Banda? Ya begitulah. Pelabuhan Semarang, pelabuhan kedua terbesar di Jawa, kebanjiran rob? Ya begitulah. Pisani sangat heran bagaimana negeri ini, negeri kepulauan super besar, bisa tetap jadi satu negara tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Di bagian Timur, negara nyaris tidak hadir. Terjadi kecemburuan sosial antara warga setempat dengan perantau dari Jawa dan Sumatra, namun mereka tetap saling menyapa dengan bahasa Indonesia. Nelayan Sangihe kadang mengganti bendera Indonesia di kapal dengan bendera Filipina agar bisa langsung menjual ikan, daripada harus berkeliling balik ke Manado. Namun tetap saja, mereka semua bersedia ikut upacara bendera, hafal Pancasila, dan gemar nonton sinetron Indonesia.
Bagian terbesar dari buku ini menggambarkan keindahan, keramahan, dan keunikan budaya Indonesia, terutama Indonesia Timur. Pisani menonton upacara kematian di Sumba yang merupakan ajang unjuk kejayaan keluarga, sekaligus penyebab utama mengapa masyarakatnya terjerat dalam kemiskinan. Di Banda, Pisani menyaksikan sisa-sisa kekejaman penjajah yang membuat kebanyakan rakyat Indonesia jadi bersifat penurut. Untuk mencapai Sangihe, Pisani menghabiskan waktu lima hari duduk di antara kontainer di atas kapal feri perintis bersama tiga ratus orang lainnya. Satu-satunya yang menahan matahari dan hujan di dek adalah atap terpal antar kontainer. Namun di antara pemandangan laut yang menakjubkan, polusi suara musik dangdut dari radio boombox, dan obrolan ngalor-ngidul sekelompok pemuda mabuk, Pisani mencatat hal luar biasa mengenai Indonesia.
Manusia Indonesia sangat ulet. Gabungan antara ‘ya sudahlah’, sikap hidup santai menerima kondisi, kebiasaan berkelana dan berdagang yang mendarah daging, keramahan pada orang asing, secara umum membentuk karakter manusia Indonesia. Pisani tidak meromantisasi keramahan orang Indonesia. Bukunya juga memuat kisah-kisah tragis berbagai konflik yang terjadi paska kemerdekaan: pemberontakan-pemberontakan daerah, konflik GAM di Aceh, pembantaian etnis Madura di Kalimantan, konflik Islam-Kristen di Maluku, pengusiran penganut Ahmadiyah di Lombok, sampai Tragedi Mei 98. Pisani menyimpulkan bahwa di balik keramahan, orang Indonesia juga mampu bertindak brutal ‘jika diperlukan’. Jaringan sosial dan politik rumit memaksa siapapun yang menjadi pemimpin masyarakat harus bisa jungkir balik menjaga keseimbangan. Hubungan cinta-benci antara penguasa dengan ‘preman bayangan’ menjadi sebuah kewajaran dalam politik Indonesia, dan kekepoan orang Indonesia untuk selalu bertanya ‘dari mana? agamamu apa?’ pada orang baru adalah mekanisme pertahanan diri untuk menghindari potensi konflik.
Di akhir buku, Pisani mengangkat kisah sukses Surabaya memerangi sampah. Dia memberi catatan khusus tentang keberhasilan ini: ternyata orang Jawa bisa juga melakukan perubahan besar tanpa lewat pemaksaan kekuasaan ala Orba, melainkan lewat kultur pemberdayaan positif.
Sungguh buku yang sangat memuaskan hati dan mengenyangkan pikiran! Saya berharap buku ini bisa diterjemahkan, bahkan difilmkan. Walaupun saya kurang tahu apakah sensor ala Orba masih berlaku saat ini, karena buku ini memuat nama-nama besar yang pasti tidak akan suka kalau dikaitkan dengan isu politik sensitif seperti yang diceritakan di buku ini. Saya juga penasaran, apa kata Bu Pisani kalau melihat Indonesia sekarang, lebih baik kah atau ‘ya begitulah’?
Yuk, baca bukunya dan jatuh cinta lagi pada Indonesia!