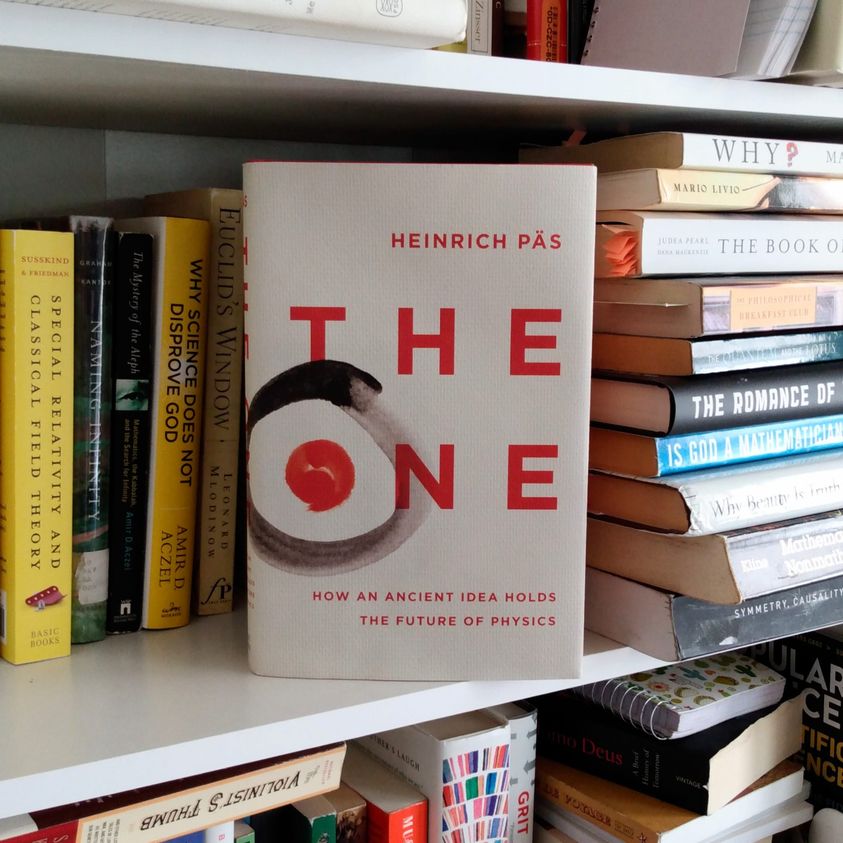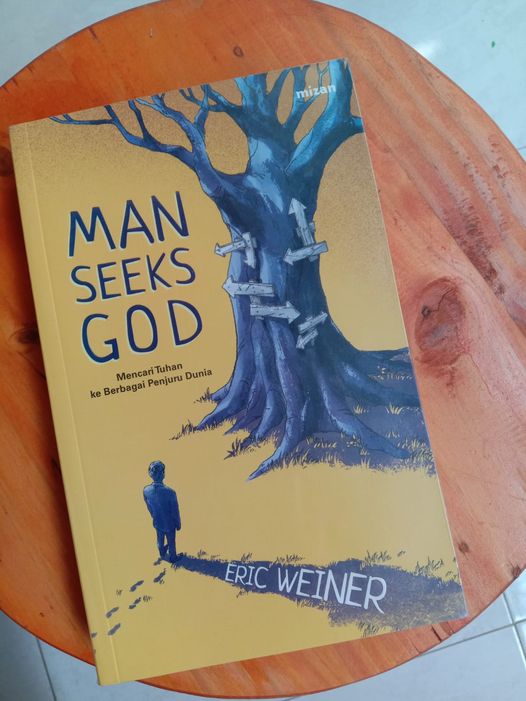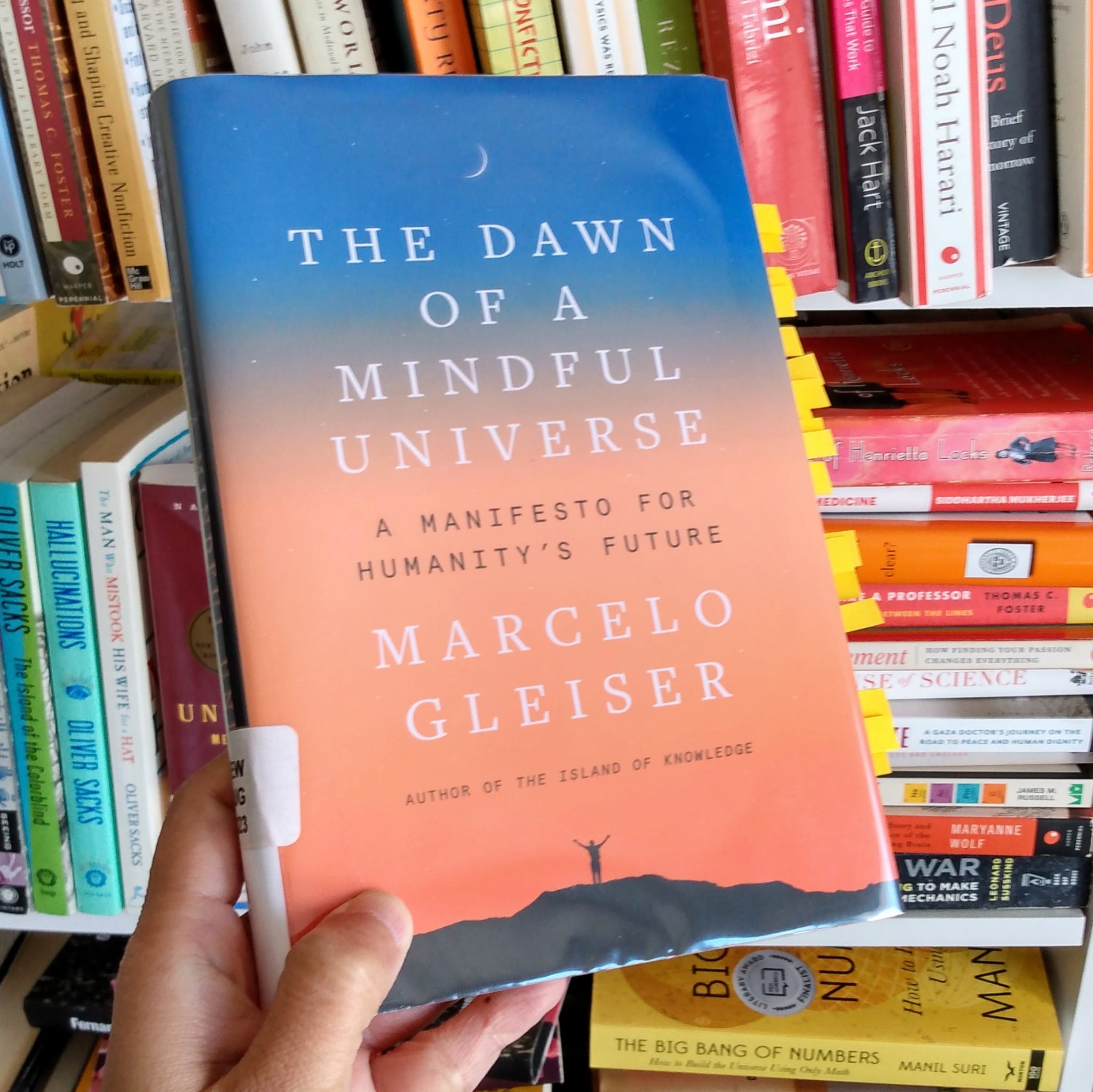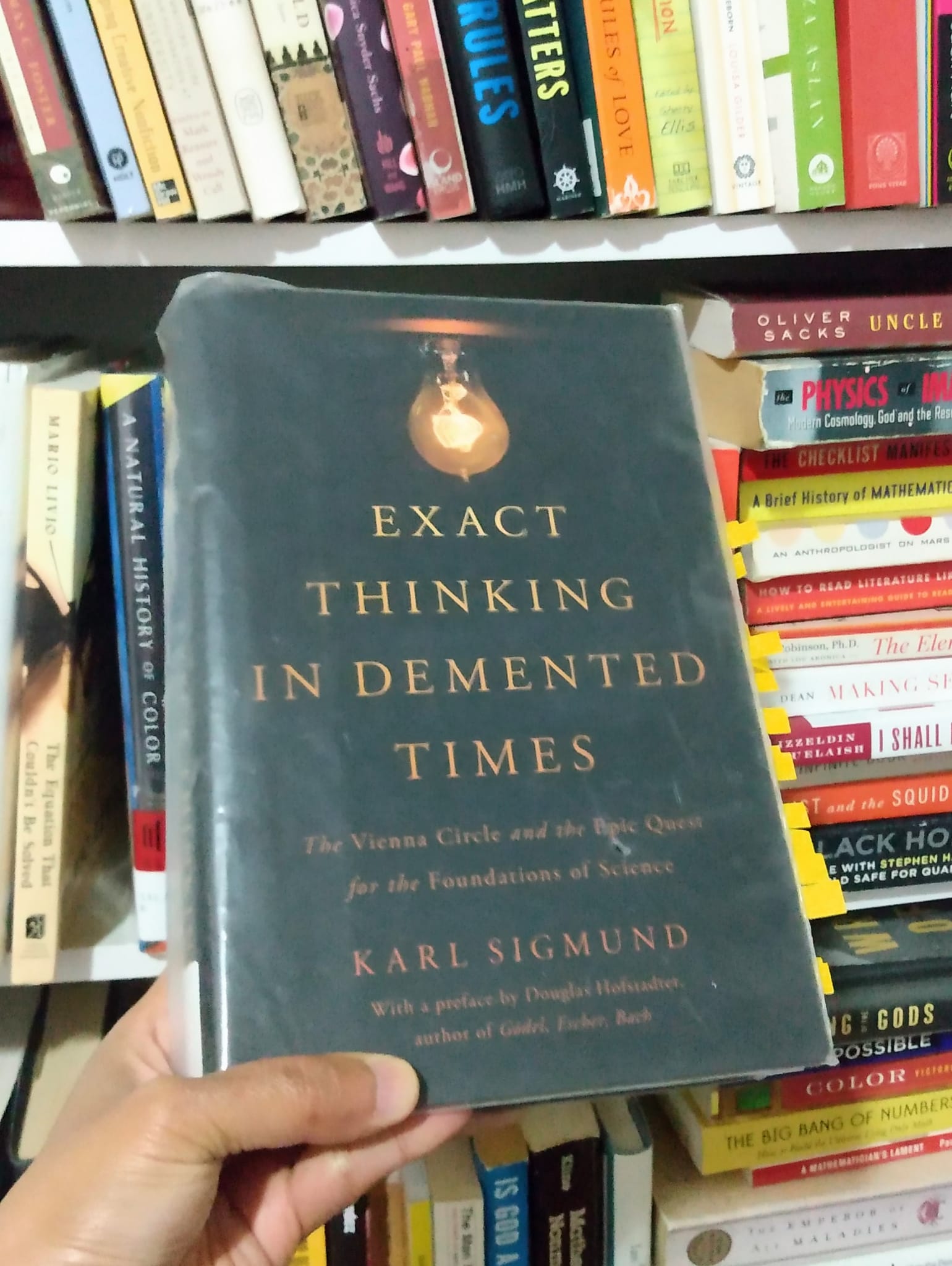== Membaca buku ini, yang ada di kepala saya adalah “Forget what you think you know about reality. Forget it!” Silakan baca review ini dan teman-teman akan mengerti kenapa ===
The One: How An Ancient Idea Holds The Future of Physics
Heinrich Päs
Basic Books (2023)
358 hal
Heinrich Päs adalah fisikawan Jerman dan profesor fisika teori di TU Dortmund University, pernah mengajar di beberapa universitas di Amerika, dan melakukan riset di CERN dan Fermilab. Di bangku SMA ia memutuskan mendalami dunia fisika karena ingin tahu “What is everything made of?”. Puluhan tahun ia berkecimpung di dunia fisika partikel untuk mencari jawabannya. Tapi…”Now I believe we are on the wrong track.”
Jangan salah sangka dulu, katanya. Maksudnya bukan fisikanya yang salah. “Meskipun fisika partikel tetap yang paling presisi di dunia sains, namun dia tidak menjelaskan keseluruhannya. It doesn’t tell the full story,” jelasnya.
Sejak ditemukannya atom, fisika mengikuti paradigma reduksionsime, yaitu bahwa segala sesuatu dapat dipahami dengan mereduksinya menjadi bagian-bagian terkecilnya. Bahwa segala sesuatu pada akhirnya sama, tersusun dari atom, yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron, di mana proton dan neutron terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil lagi yaitu quark.
Namun ini tidak lengkap, karena partikel elementer mengikuti aturan mekanika kuantum. Sistem kuantum mengikuti prinsip superposisi, di mana suatu partikel pada saat yang sama memiliki lebih dari satu posisi yang saling terkait dan tidak terpisahkan (entangled) sebelum diamati, dan kesemuanya itu adalah bagian dari realitas, tidak bisa diabaikan begitu saja.
Tafsiran Copenhagen atas mekanika kuantum (dari Niels Bohr & Werner Heisenberg), yang selama ini paling banyak diterima dan diaplikasikan di fisika, mengatakan bahwa pada saat partikel diamati, prinsip superposisi ‘runtuh’ karena terjadi ‘decoherence’ sehingga menghasilkan satu posisi saja, dan posisi inilah yang dianggap ‘real’. Meskipun aplikasi tafsiran ini bermanfaat dan telah memajukan ilmu pengetahuan dengan sukses, namun sekali lagi, menurut Päs, mengabaikan prinsip superposisi berarti tidak menjelaskan realitas secara lengkap, bahkan ‘in denial of reality’.
Tafsiran lain datang dari Hugh Everett III, yang kemudian dikenal dengan tafsiran Many Worlds. Dalam tafsiran ini, prinsip superposisi tidak diabaikan. Saat partikel diamati dan posisinya menjadi eksak, posisi-posisi lainnya tetap ada tetapi ‘bercabang’ ke dunia paralel. Tafsiran ini sebenarnya tafsiran yang paling simpel dari persamaan Schroedinger, namun pada saat itu ditolak dan dianggap gila.
Namun sekarang justru tafsiran Many Worlds inilah yang semakin banyak ‘penganut’nya, karena merupakan tafsiran paling harfiah dari mekanika kuantum, tanpa ada asumsi tambahan ini itu, sehingga paling dekat menjelaskan realitas yang sebenarnya.
Heinrich Päs menganalogikan realitas seperti ini: apakah realitas itu film di layar bioskop, ataukah rol film yang diproyeksikan oleh cahaya di dalam proyektor? Semesta dalam tafsiran Copenhagen itu seperti film di layar, merupakan satu perspektif saja yang dapat kita tangkap dan alami. Sementara tafsiran Many World menganggap bahwa realitas yang sesungguhnya itu lebih besar dan tersembunyi dari persepsi kita.
Analogi seperti ini bukan hal baru. Ribuan tahun yang lalu filsuf Yunani Plato menyampaikan “Allegory of the Cave”, yang menganalogikan dunia ini seperti bayangan di dinding gua, dan penghuninya menganggapnya realitas, karena tidak bisa melihat sumber bayangan yang merupakan realitas sebenarnya. Päs juga menganalogikannya seperti wayang. Bayangan wayang di layar dianggap cerita yang nyata, padahal terbentuk dari benda/karakter yang justru menutup sumber cahayanya.
Begitu pula tafsiran Copenhagen yang, menurut Päs, hanya fokus di satu perspektif realitas yang justru menghalangi kita dari melihat realitas sesungguhnya. Dengan tafsiran ini, Bohr dkk memisahkan dunia menjadi makroskopik (fisika klasik yang dianggap ‘nyata’) dengan mikroskopik (fisika kuantum yang ke’nyata’annya diabaikan).
Päs lalu bertanya-tanya mengapa Bohr memilih tafsiran seperti itu, memisahkan dunia seolah-olah superposisi tidak ada. Kalau memang serius ingin memahami realitas, semuanya harus diakui keberadaannya, meskipun tidak intuitif atau aneh. Bagaimanapun, itulah konsekuensi mekanika kuantum.
Dalam bab “The Struggle for One” ia menelusuri sejarah kepercayaan manusia, bagaimana pada awalnya manusia menganggap dirinya satu kesatuan dengan alam. Filosofi ini disebut monism. Meskipun kepercayaan awal itu seringkali dikatakan sebagai polytheism, namun sebenarnya itu wujud kepercayaan bahwa ada ‘the One’ bersemayam di setiap wujud, bukan ada ‘banyak tuhan’. Polytheism sebenarnya adalah cosmotheism atau pantheism, yaitu bentuk monism. Perbedaan monism dengan monotheism, yang terakhir ini mempercayai bahwa Tuhan mengatur dari luar, beda dengan makhluk (walaupun aliran sufistik/mysticism dari masing-masing agama monotheistik juga sebenarnya cenderung monism).
Kalau mengamati sejarah, orang-orang yang mengusung filosofi monism selalu dianggap sesat bahkan dipersekusi oleh pihak penguasa negara maupun agama karena dianggap ‘melawan dan merendahkan Tuhan’ (seperti Copernicus, Giordano Bruno, Galileo, dll). Padahal, berpikir dalam kerangka monistik telah memandu banyak ilmuwan menemukan keteraturan semesta yang universal. Maka tidak heran jika akhirnya sains merasa perlu menjauhkan diri dari agama, dan Bohr menolak tafsiran yang menggunakan ‘bahasa’ yang sama dengan agama. “We ought to remember that religion uses language in a quite different way from science,” kata Bohr dalam diskusinya dengan Heisenberg.
Tapi menurut Päs, jika kita menganggap serius mekanika kuantum, maka itu berarti di level paling fundamental, semesta tidak bisa terbagi-bagi menjadi bagian individu yang berdiri sendiri. Saat ini fisika kuantum modern memahami partikel bukan sebagai objek yang solid seperti dalam fisika klasik. Partikel kuantum lebih tepat digambarkan sebagai gumpalan energi atau disebut quanta. Sifatnya bukan objek tertentu yang punya posisi definitif. Dan medan kuantum (quantum field) ini tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya (entangled). Karenanya, “The most fundamental description of the universe has to start with the universe itself,” Päs menekankan. Deskripsi realitas harus dimulai dari kosmologi kuantum, menganggap keseluruhan semesta sebagai satu sistem kuantum. The One.
Ketika paradigma ini diikuti oleh fisikawan, mereka menemukan hal-hal yang ‘aneh’ dan membingungkan. Tahun 1967 John Wheeler dan Bryce DeWitt mencoba menerapkan fungsi gelombang ke keseluruhan semesta, apa yang terjadi? Mereka menemukan bahwa di level kuantum, semesta ini statis, tidak berubah, ‘timeless’, bisa dibilang kekal abadi. “Nothing happens” kata mereka.
Apa lagi? Di level kuantum, karena sifat entanglement, satu partikel bisa berada di lebih dari satu tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, bahkan ketika terpisah jarak yang sangat jauh. Ini dinamakan bersifat ‘non-lokal’. Saat ini fisikawan pun mulai berpikir bahwa ruang-waktu pun tidak fundamental seperti yang dikira sebelumnya, melainkan emergent, merupakan gambaran geometrik bagaimana objek-objek di dunia kuantum terkait dalam entanglement. Justru entanglement-lah kunci dari realitas ini.
Begitulah dunia kuantum, yang sebenarnya adalah realitas dunia kita. Ternyata materi, ruang, dan waktu tidaklah nyata, hanya ilusi. “I’m almost certain that space and time are illusions. These are primitive notions that will be replaced by something more sophisticated,” menurut Nathan Seiberg, fisikawan teori Princeton.
Tapi, tidakkah kita ini nyata? Berupa materi yang berada di ruang dan bergerak seiring waktu? Ya, kita mengalami semua ini karena indera kita adalah bagian dari fisika klasik. Bisa dikatakan, dunia ini menjadi nyata, karena ada kita sebagai pengamatnya, begitu menurut participatory principle dari John Wheeler.
Tidak masuk akal? Mungkin akal kitalah yang harus lebih rendah hati “Wow, begitu banyak yang tidak saya mengerti di alam semesta ini!”
Tidak disangka ya, fisika semakin modern kok makin terdengar sangat spiritual, seperti apa yang selama ini disampaikan para sufi dan mystic. Bahwa dunia ini ilusi, bahwa pada hakikatnya hanya ada satu eksistensi. Inikah artinya “Tuhan lebih dekat dari urat nadi” itu?
Menurut Päs, “We need to accept nature as it is… not project one’s preconceived notions onto nature.”
Hal yang sama dituliskan Carlo Rovelli di buku Helgoland: “I believe that we need to adapt our philosophy to our science, and not our science to our philosophy.”
“Sudah waktunya sains ‘berbaikan’ dengan konsep “The One” jika serius ingin memahami realitas” tulis Päs menutup buku ini.