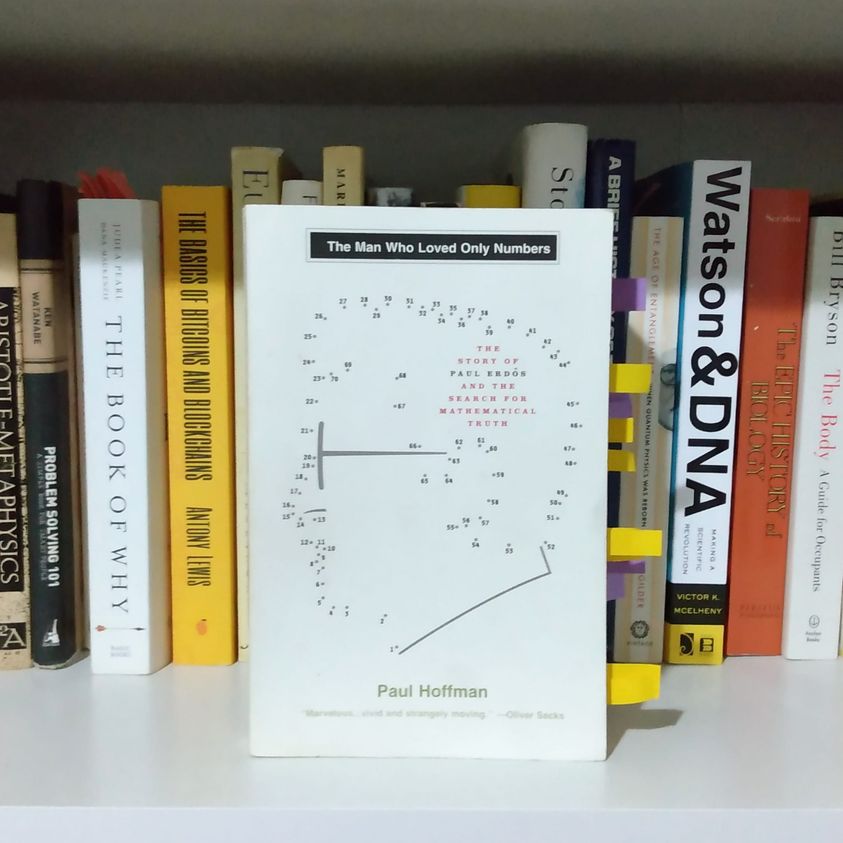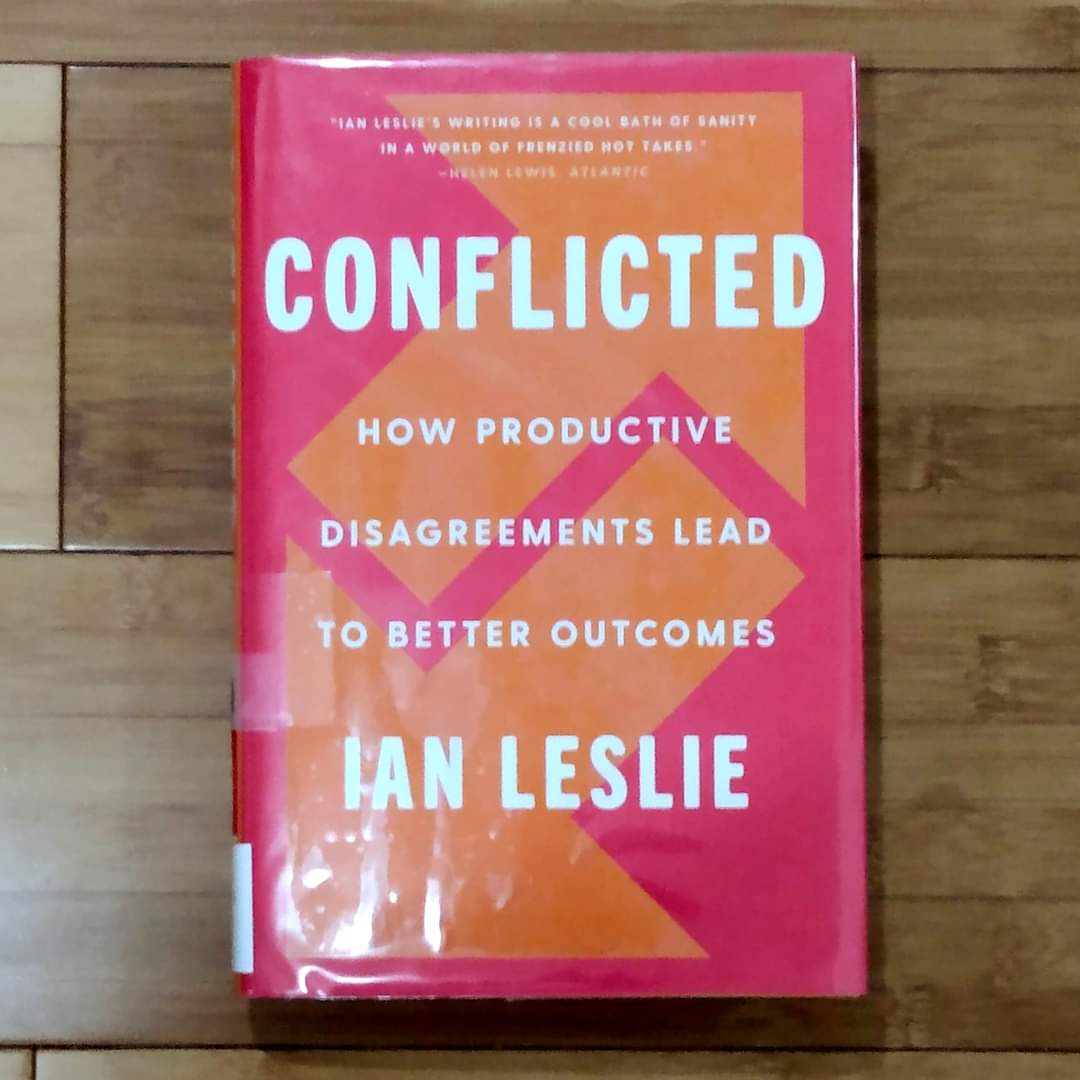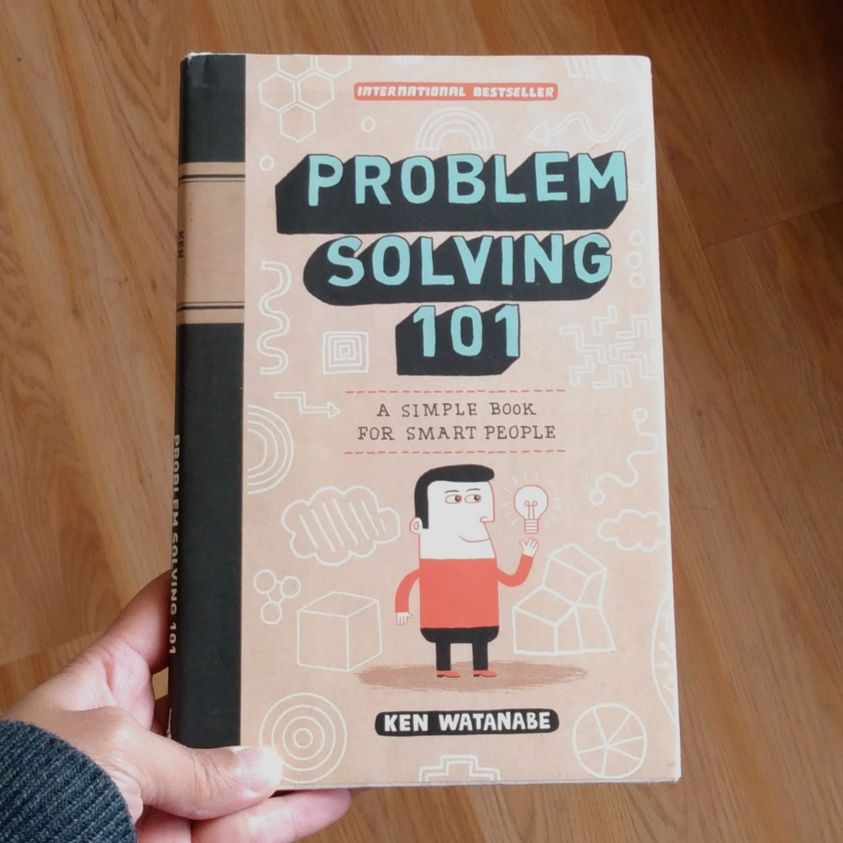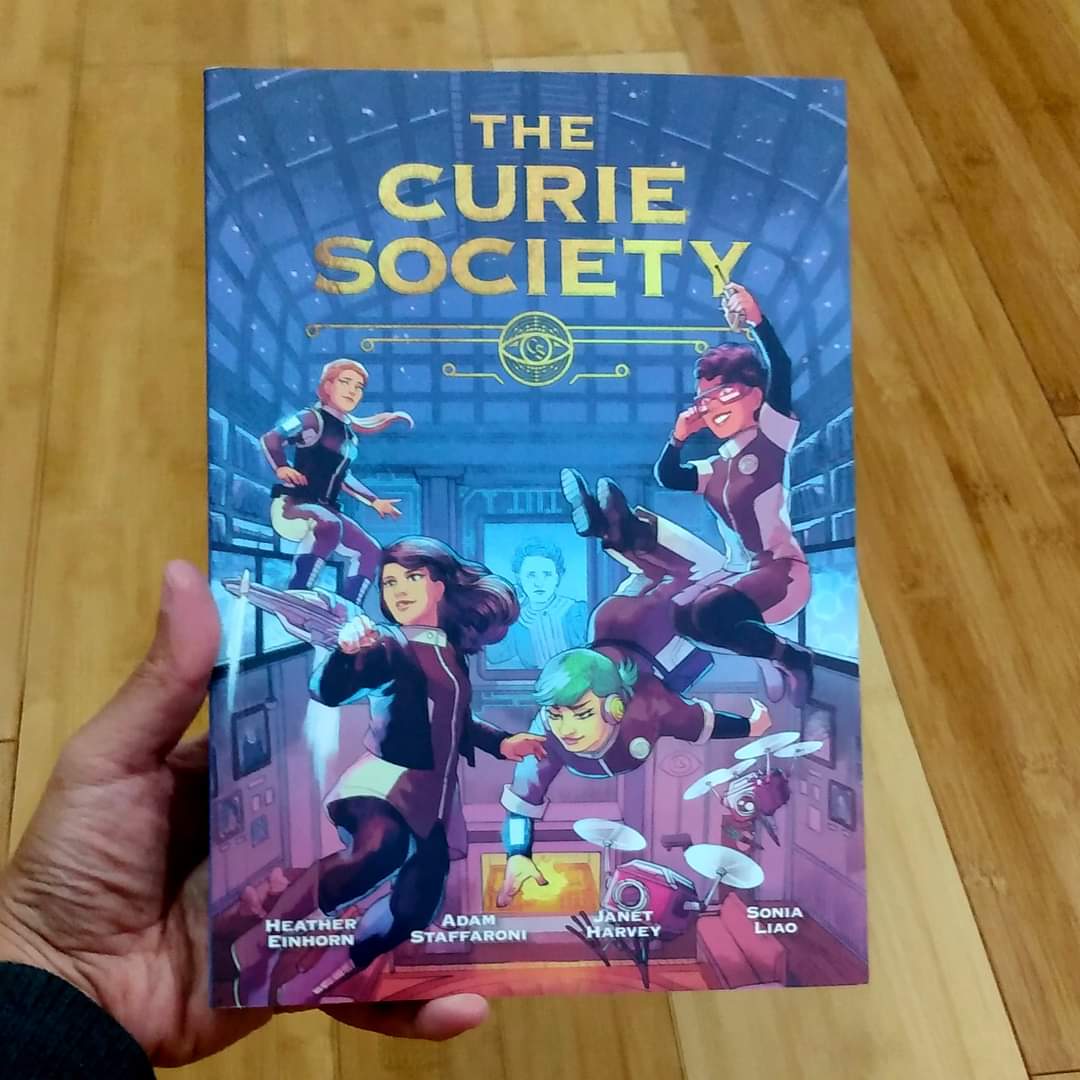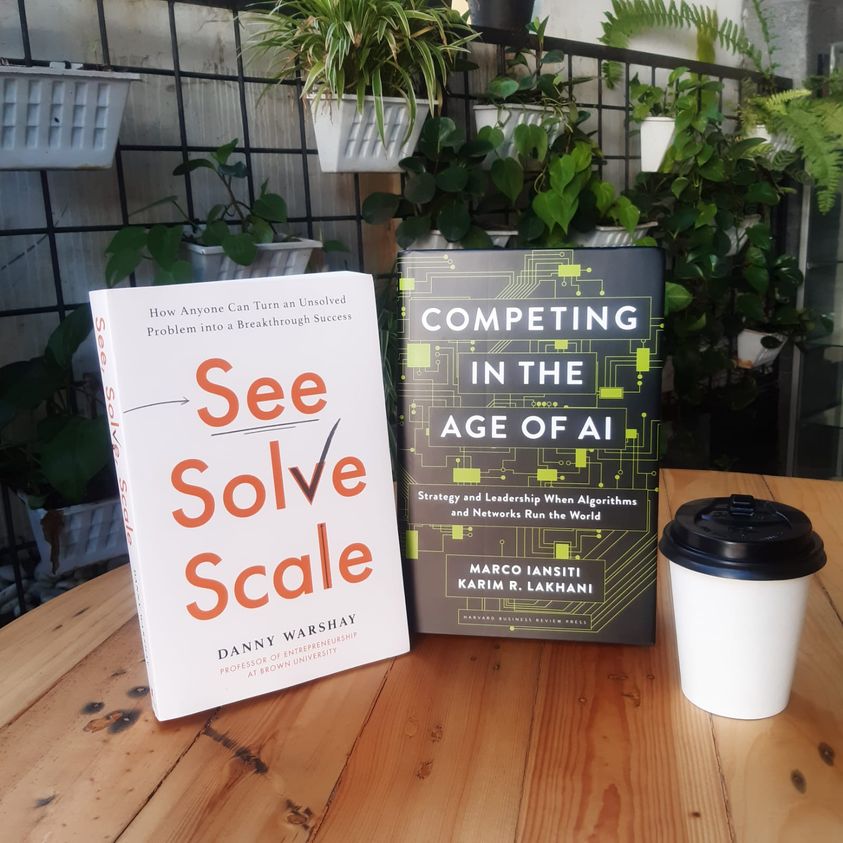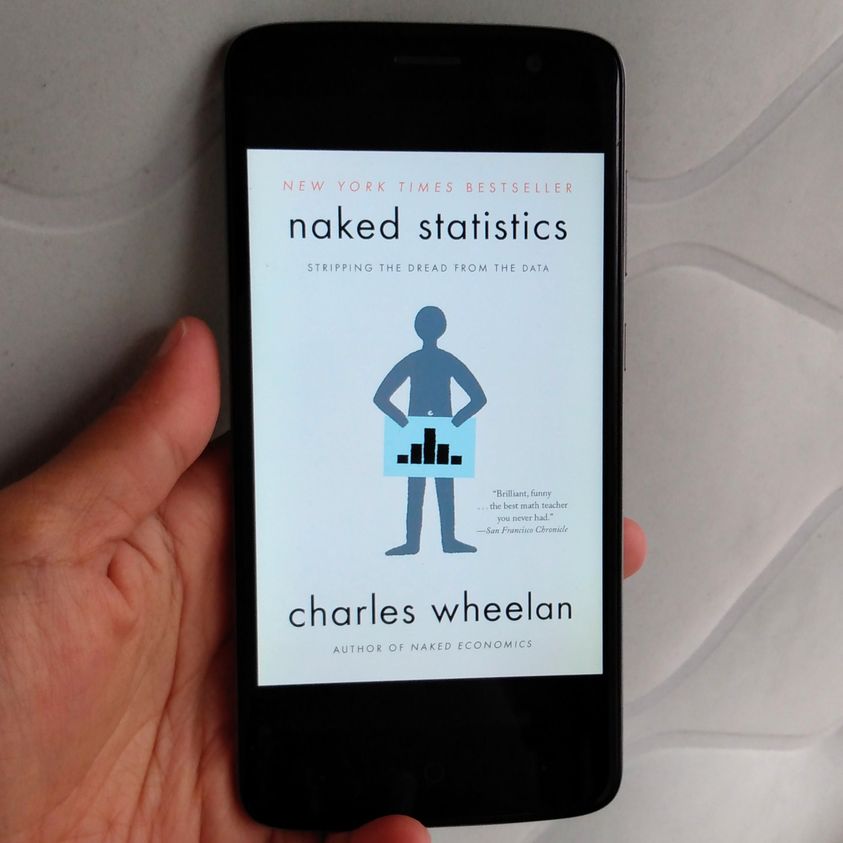Tahun 2005, Larry Summers, presiden Harvard saat itu berkomentar mengenai gender gap di dunia sains dan mengajukan pertanyaan ‘mengapa hanya ada sedikit perempuan di jajaran puncak akademik dan profesional bidang sains?’ dan mengajukan argumen bahwa salah satu faktornya mungkin adalah perbedaan kemampuan alami bidang sains dan matematika. Pernyataan itu membuat marah banyak pihak, terutama perempuan, dan masih menjadi bahan perdebatan sampai sekarang.
Eileen Pollack, penulis yang juga berlatar belakang ilmu fisika, menumpahkan pemikirannya tentang ‘mengapa tidak banyak perempuan yang mengambil jurusan/profesi sains’.
The Only Woman in the Room: Why Science is Still A Boy’s Club
Eileen Pollack
Beacon Press (2015)
266 hal
Eileen Pollack adalah penulis, profesor creative writing di University of Michigan dan mengepalai program Master of Fine Arts di sana. Meskipun berkecimpung di dunia kepenulisan, namun latar belakang S1nya adalah fisika teori di Yale University. Buku ini berupa memoar, refleksi pengalaman hidupnya sebagai gadis jenius yang ambisius dengan ketertarikan besar mendalami fisika yang penuh dengan misteri. Namun dalam perjalanannya sebagai satu dari 2 perempuan pertama di jurusan Fisika Yale University, dan bahkan meraih summa cum laude, ia kemudian memutuskan untuk menjadi penulis, bukan ilmuwan bidang fisika.
Buku ini terbagi menjadi 3 bagian besar yang mencakup kehidupannya sebelum kuliah di Yale, selama kuliah, dan ketika kembali ke Yale dan kota kelahirannya puluhan tahun kemudian untuk riset tentang buku ini.
Eileen lahir tahun 1956 di keluarga Yahudi di kota kecil di pegunungan Catskill di upstate New York, yang terkenal dengan nama “Borscht Belt” yaitu daerah di mana banyak imigran Yahudi Eropa Timur. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat akademiknya. Namun sayangnya, seperti banyak terjadi di antara anak-anak highly gifted yang disalahpahami, ia merasa bosan di kelas yang dianggap terlalu mudah. Sedikit-sedikit bertanya ini itu pada guru, membuat guru jengkel, jadi berulah di kelas dan dicap ‘anak nakal’ oleh guru-gurunya.
Eileen berprestasi di sekolah, ‘the smartest girl’ yang membawa sekolahnya juara lomba debat, punya rasa ingin tahu yang tinggi, ambisius, dan selalu ingin menang dan membuktikan diri bahwa ia bisa.
“I loved competing. How else could I prove to the brilliant, powerful men who ruled the world that I was as smart and strong as they were?”.
Namun dalam pergaulan sosial, ia dikucilkan oleh teman-teman perempuannya. Pura-pura diundang ke pesta yang kosong, diolok-olok, dibilang “cowok nggak ada yang mau sama cewek yang lebih pintar”, dll. Akhirnya dia lebih senang bergaul dengan sesama ‘nerds’ (yang rata-rata laki-laki), atau menghabiskan waktu sendiri membaca novel sci-fi, dan berpikir tentang alam semesta.
Lulus SMA, Eileen diterima di 5 kampus Ivy League, juga MIT. Atas berbagai pertimbangan, ia memutuskan memilih Yale University dan mengambil jurusan fisika. Di Yale ia juga merasa terkucil. Sebagai satu dari hanya 2 perempuan jurusan fisika (tahun 70an), dari sekolah negri di kota kecil, minoritas Yahudi, tidak banyak tahu pop-culture, dia merasa ‘nggak nyambung’ di mana-mana.
Awalnya ia sulit mengikuti, karena teman-temannya rata-rata datang dari sekolah elit di kota besar yang sudah dapat pelajaran fisika lanjut, sementara ia dari kota kecil yang hanya mendapat pelajaran fisika dasar.
Eileen tidak suka cara belajar fisika di mana dosen hanya mengajarkan bagaimana memakai rumus ini dan itu tanpa menerangkan untuk apanya. “Seperti disuruh benerin mobil tapi nggak dikasih tau gimana kerja mesinnya!”. Apalagi soal-soalnya memakai contoh-contoh yang ‘cowok banget’ seperti pesawat tempur, senapan, atau baseball.
“Studying physics, as it turned out, didn’t involve the contemplation of space and time, as I had hoped,” tulisnya. Ia lebih suka berpikir teoritik dibanding melakukan eksperimen. Tapi Eileen bekerja keras mengejar ketinggalan dengan belajar sendiri dari buku-buku di perpus, dan dari sini ia memahami prinsip-prinsip fisika yang diwakili oleh rumus-rumus tadi.
“When confronted with a problem, you shouldn’t just plug the data into some equation. Rather, you should close your eyes and visualize the objects in the problem moving and interacting.”
Di Yale yang merupakan liberal arts college, selain mengambil jurusan fisika, Eileen juga mengambil mata kuliah bidang lain seperti psikologi dan filsafat (karena ia penasaran dengan otak manusia, bagaimana proses berpikir, dan apa itu consciousness). Suatu hari seorang profesornya menyarankan Eileen mengeksplorasi minatnya sebelum memutuskan fokus di fisika. “Aren’t there other things you like to do beside physics?”. Eileen yang senang menulis dan sering mengirim artikel ke majalah kampus, kemudian mengambil kelas seminar nonfiction writing. Tidak hanya brilyan di jurusan fisika (ia pernah diundang secara pribadi oleh John Wheeler untuk mempresentasikan risetnya di konferensi fisika teori, dan duduk semeja dengan para pemenang Nobel Steven Weinberg dan Ilya Prigogine), ternyata ia pun berbakat menulis, dipuji-puji dosennya dan direkomendasikan untuk mengambil kelas terbatas yang diajar oleh John Hersey, penulis senior pemenang Pulitzer.
Tidak seperti di jurusan fisika di mana Eileen tidak merasa kompeten terutama di laboratorium (meskipun nilainya tetap bagus), dan juga tidak mendapat dorongan semangat dari para dosen sehingga selalu meragukan kemampuannya, di kelas menulis ia merasa mendapat penghargaan dan dukungan besar dari teman-teman dan dosen-dosennya. Mereka menyatakan ia berbakat menulis, bahkan penulis sekaliber John Hersey pun mengakui bakatnya. Ia yang merasa sendiri di jurusan fisika, sebaliknya merasa banyak teman di kelas menulis dan filsafat. Inilah salah satu alasan mengapa akhirnya ia memutuskan untuk memilih profesi penulis.
Alasan lainnya adalah kekecewaannya ketika menyadari bahwa riset fisika sering dipakai untuk hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya tanpa diberi tahu sebelumnya. Eileen sempat magang di divisi fisika partikel Oak Ridge National Laboratory dengan tugas merancang simulasi komputer yang dapat memprediksi pola radiasi reaktor nuklir. Namun setelah selesai ia baru tahu bahwa hasil kerjanya akan digunakan oleh militer untuk memprediksi pola radiasi bom nuklir.
(Cerita ini nyambung sekali dengan film Oppenheimer. Oak Ridge adalah salah satu fasilitas yang didirikan untuk riset bom atom Manhattan Project. Tim Oak Ridge dipimpin oleh Enrico Fermi yang bertugas mengembangkan reaktor nuklir untuk memproduksi plutonium.
Perasaan Eileen ini seperti kegoncangan batin Oppenheimer dan para ilmuwan yang bekerja di Manhattan Project, yang terpecah antara memuaskan keingintahuan memecahkan misteri semesta (bagaimana fisi nuklir bekerja? energi seperti apa yang dihasilkan dalam sebuah bom atom?) dan menyadari kenyataan bahwa hasil kerja mereka ternyata digunakan untuk menghancurkan dan membunuh begitu banyak orang tak bersalah).
Lulus dari Yale dengan summa cum laude, Eileen memutuskan melanjutkan pendidikan bidang creative writing. Orang tuanya bingung dan agak kecewa, belajar fisika berat-berat di kampus Ivy League, tapi lalu jadi penulis? Namun seorang profesor fisikanya memberi dukungan, “That’s terrific! The world can always use more writers who understand physics”. (Wah setuju banget nih!)
Puluhan tahun kemudian ia kembali ke Yale dan kota kelahirannya untuk riset buku ini, mewawancara para guru, dosen, dan mahasiswa jurusan sains tentang situasi yang dihadapi perempuan di bidang sains. Yale dan Amerika pada umumnya sekarang sudah banyak berubah dibandingkan jaman Eileen sekolah. Perempuan semakin banyak mengambil jurusan sains. Ada 30-40% mahasiswi di jurusan fisika Yale sekarang, bahkan departemen fisika Yale dipimpin oleh Meg Urry, seorang astrofisikawati.
Yang cukup menarik adalah wawancaranya dengan salah satu profesor fisikanya dulu, profesor Nemethy yang berasal dari Hungaria. Menurutnya di Eropa dari sejak lama tidak aneh kalau perempuan terjun ke dunia sains. Ia heran kok Amerika lama sekali untuk sampai ke tahap ini (Saya juga heran, soalnya jaman ibu saya di ITB tahun 60an sudah banyak perempuannya). Dari wawancara Eileen dengan mahasiswa-mahasiswa dari Eropa dan Asia juga komentarnya seperti itu. Sementara para mahasiswi sains asal Amerika mengatakan bahwa jaman mereka sekolah (terutama di middle school/SMP), ada peer pressure bahwa murid yang senang sains dan matematika itu aneh, nerd, bahkan tidak jarang dibully. Seorang mahasiswi curhat, bahwa di kelas AP Physics di SMA dia diolok-olok teman-temannya “You’re a girl, we don’t need to listen to you. Girls can’t do physics!”.
Seperti di film-film Hollywood tema high school ya, yang ‘cool’ itu para olahragawan dan cheerleaders, sementara para nerds jadi bahan olok-olok. Eileen menyoroti film seri Big Bang Theory di mana para nerds ini meskipun disoroti kepintarannya, namun sekaligus jadi bahan tertawaan. Jadi apakah budaya Amerika tentang ini benar-benar sudah berubah? Jangan-jangan belum…
Dari berbagai wawancara dan riset tentang gender gap di bidang sains ini, Eileen menyimpulkan bahwa faktor terbesar mengapa tidak banyak perempuan terjun ke dunia sains sebenarnya adalah faktor psikologis dan kultural, bukan biologis. Dari segi kemampuan, ya, perempuan juga mampu bersaing di bidang sains, namun seringkali yang menjadi penghalang adalah peer pressure dari lingkungan, pandangan-pandangan tradisional, dan ketidaktersediaan infrastruktur (misalnya fasilitas childcare yang memungkinkan mereka menjalani karir bidang sains sekaligus menjalankan tugasnya sebagai ibu).
Meg Urry beropini bahwa “women were leaving the profession not because they weren’t gifted but because of the slow drumbeat of being underappreciated, feeling uncomfortable and encountering roadblocks along the path to success”.
Perempuan perlu lebih percaya diri akan kemampuannya. “They might need to become more confident, less needing of encouragement, more eager to support each other,” tulis Eileen, “(but) the larger society (also) needs to change”. Suasana kerja yang ramah bagi perempuan (tidak penuh dengan orang-orang yang saling melontarkan komentar seksis atau candaan vulgar), ketersediaan network dan support system, akan mendorong ketertarikan perempuan terjun ke dunia sains.
==========
Membaca buku ini seringkali saya agak sulit relate dengan pengalaman bu Eileen, mungkin karena saya tumbuh di masa dan di lingkungan di mana banyak sekali perempuan yang menempuh studi bidang sains dan teknologi dan masyarakat menganggapnya normal saja. Bahkan jaman ibu saya kuliah di ITB pun (tahun 60an) sudah banyak perempuannya. Mungkin karena budaya Asia dalam hal ini berbeda dengan Amerika? Atau mungkin saya memang hidup dalam sebuah ‘privilege bubble’ yang sempit dan relatif progresif? Saya tidak tahu jawaban tepatnya.
Kalau mengandalkan emosi, dan bukan data, tentu mudah sekali tersulut dengan topik yang dibahas di buku ini. Banyak perempuan akan marah disebut kemampuan berpikir sains dan matematikanya kalah dibanding laki-laki, dan mengajukan ‘bukti’ tokoh-tokoh ilmuwan perempuan sepanjang sejarah. Namun sekali lagi, kita perlu data untuk menganalisa ‘apa benar ada perbedaan intrinsik antara laki-laki dan perempuan’. Well, saya pikir memang ada perbedaan, hanya saja tidak sesimpel itu.
Ingat bahasan tipe-tipe otak dan teori Empathizing-Systemizing hasil penelitian psikolog Cambridge Simon Baron-Cohen yang pernah dibahas di buku Pattern Seekers?(*) Studi dengan sampel setengah juta orang ini mengukur Systemizing Quotient (SQ) dan Empathizing Quotient (EQ). SQ mengukur level ketertarikan terhadap sistem (yang senang mencari tahu bagaimana suatu hal bekerja, bagaimana membangun dan memperbaiki suatu sistem, fokus urusan presisi, detail, akurasi, hal-hal yang krusial dalam dunia saintek). EQ mengukur cognitive empathy, sensitivitas seseorang terhadap apa yang dipikirkan atau dirasakan orang lain. Bisa dikatakan, SQ punya karakteristik maskulin (aktif, asertif, tegas, dll), dan EQ punya karakteristik feminin (pasif, intuitif, sensitif, lembut, dll). Maskulin-feminin di sini konteksnya sifat/karakter, BUKAN JENIS KELAMIN.
Dalam studi itu fokus studi adalah otaknya, baru setelah itu dilihat perbedaan jenis kelamin pemilik tipe-tipe otaknya. Ternyata yang kuat EQnya kebanyakan perempuan, dan yang kuat SQnya kebanyakan laki-laki. Jadi memang secara umum, ada perbedaan. Tetapi kita harus fokus di kata KEBANYAKAN, yang artinya TIDAK SEMUANYA. Dalam studi Baron-Cohen, ditemukan bahwa SETIAP orang memiliki EQ dan SQ dengan komposisi berbeda yang tarik menarik. Semakin kuat EQnya, semakin lemah SQnya, dan sebaliknya. Ada juga yang kekuatan EQ dan SQnya seimbang. Dan semua ini TANPA MEMANDANG JENIS KELAMINNYA.
Riset Baron-Cohen juga mengatakan bahwa bagaimana otak berkembang menjadi tipe satu dan lainnya, dipengaruhi level hormon testosteron & estrogen di dalam rahim ketika fetus sedang tumbuh, DAN faktor genetik. Nurture tentu berpengaruh, tapi ya, harus ada gen-nya dulu. Dan rangkaian gen yang mempengaruhi sirkuit Empathizing dan Systemizing itu berbeda.
Dari sini saya menyimpulkan bahwa meskipun KEBANYAKAN perempuan punya karakteristik EQ yang kuat, namun ada sebagian yang juga seimbang kekuatan SQnya, atau malah SQnya lebih kuat dibanding EQnya. Karena itulah perempuan-perempuan ini memang berbakat di bidang sains, matematika, teknik, dan bidang-bidang yang membutuhkan analisa yang presisi, terukur, dan akurat lainnya seperti linguistik, hukum, dll.
Jadi kalau dilihat proses biologisnya, pertama-tama dari DNA jenis kelaminnya sudah tertentu (laki-laki/perempuan) ==> lalu ketika si jabang bayi berkembang, komposisi hormon dalam rahim tempat dia tumbuh menghasilkan otak dengan tipe tertentu ==> sehingga menghasilkan individu dengan jenis kelamin tertentu yang otaknya memiliki kombinasi EQ dan SQ tertentu.
Namun masalahnya, ketika dia lahir, secara kultural masyarakat HANYA melihat jenis kelaminnya, dan mengabaikan tipe otak dan bakat spesifik individunya.
Maka dari itu, menurut saya perdebatan ini tidak akan selesai-selesai jika kita hanya fokus di tampilan fisik luar (laki-laki/perempuan) TANPA mempertimbangkan faktor internalnya (otak, DNA, hormon), alias stereotyping tanpa menelusuri lebih dalam.
Dunia ini fitrahnya simetri, seimbang. Karena itu maskulinitas dan femininitas selayaknya hidup berdampingan dengan seimbang, baik antar gender maupun di dalam diri masing-masing. Juga seharusnya dihargai fungsinya dalam konteksnya masing-masing yang tidak sama, tapi bukan berarti satu lebih baik dari yang lain. Mestinya bukan saling berkompetisi, melainkan berkolaborasi dengan mengangkat kekuatan karakter masing-masing. Feminin dihargai fungsinya sebagaimana maskulin dihargai.
Jadi bagi saya pribadi, untuk masalah “Mengapa hanya sedikit perempuan di bidang sains?” ini, selama kesempatan dibuka untuk mereka yang memang tertarik ke bidang sains, disediakan infrastruktur untuk mendukung mereka, dan menghilangkan situasi dan kondisi yang tidak nyaman bagi mereka, jumlah tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting sama-sama menggunakan potensinya sebaik-baiknya (apapun itu, dan di bidang apapun), dan berkolaborasi untuk kebaikan semua.
===
Keterangan foto: buku The Only Woman in the Room diapit buku Knocking on Heaven’s Door dari Lisa Randall fisikawati teoritik Harvard, dan The Code Breaker(**) dari Walter Isaacson yang bercerita tentang Jennifer Doudna pakar biokimia peraih Nobel.
(*) Review buku Pattern Seekers
https://www.facebook.com/bookolatte/posts/pfbid05rXA4pkrXqWJksyvTibeeJWThpqYjcz5bYaprQX756YezbrFtsV8nfQsN1Cds9kbl
(**) Review buku The Code Breaker
https://www.facebook.com/bookolatte/posts/pfbid02Kg1gzyrgQXWcoHqYLbLr7tcVtQXsm4za5HpVcdyF8eKq4VxMCmR6Ekrjjvfy7kwKl